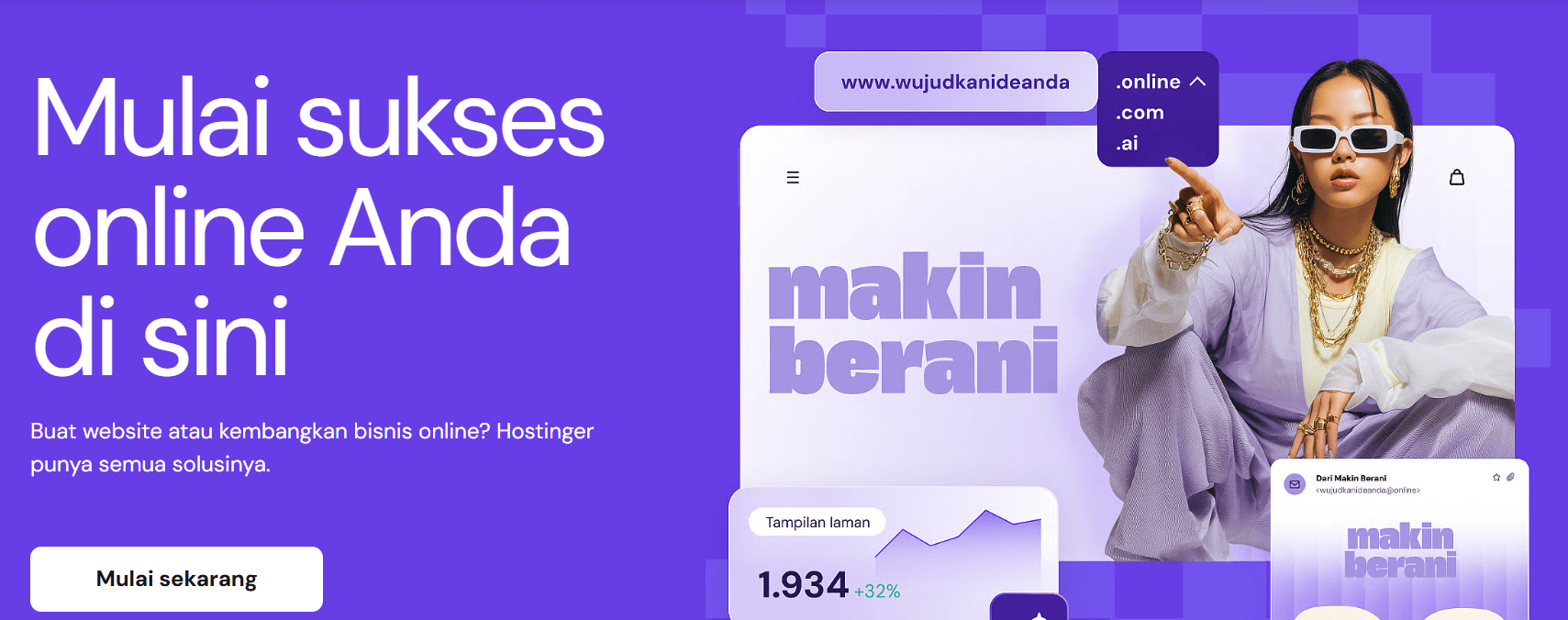Kalau bicara soal Muhammad Idris, banyak orang Jakarta daratan mungkin hanya mengenalnya lewat pemberitaan yang muncul belakangan: soal LHKPN, ayam hias, hingga tuduhan yang bahkan tidak pernah dibuktikan. Tapi kalau kita tarik ke belakang dan mendengarkan langsung ceritanya, sosok ini justru tidak pernah bercita-cita jadi anggota dewan.
Idris sudah lama dikenal sebagai pengusaha. Hidupnya cukup, keluarganya terjaga, dan komunitas hobi yang ia bangun berkembang. Dia sendiri pernah mengaku, politik itu bukan tempat aman bagi orang seperti dirinya. Sorotan akan datang dari segala arah, risiko fitnah terbuka lebar, dan bisnis yang ia jalani bisa terbengkalai. Karena itu, menjadi anggota DPRD sama sekali bukan rencana hidupnya.
Namun desakan masyarakat Pulau Seribu mengubah jalan pikirannya. Warga merasa butuh perwakilan yang benar-benar mereka kenal, bukan orang kota yang hanya muncul saat kampanye. Idris yang selama ini ada di tengah mereka, dianggap paling layak maju. Dari situlah dia akhirnya menerima amanah, bukan karena ambisi pribadi, tapi karena ada tanggung jawab moral.
Begitu duduk di kursi DPRD DKI Jakarta, Idris tidak mengubah gaya hidupnya. Ia tetap lebih sering turun ke pulau-pulau daripada nongkrong di gedung parlemen. Reses bukan sekadar formalitas, tapi jadi ruang untuk mendengar keluhan konkret: air bersih yang susah, posyandu yang kurang dukungan, akses pendidikan yang terbatas, hingga masalah sederhana seperti tempat pemakaman yang layak. Dari situ lahir usulan soal lahan TPU di Pulau Kelapa dan dorongan menghadirkan ambulans laut. Bagi orang kota mungkin sepele, tapi bagi masyarakat kepulauan ini kebutuhan vital. Bahkan urusan sampah pun ia soroti lewat sidak ke TPS, karena ia tahu betul hidup bersih di pulau kecil tidak bisa ditunda.
Lalu datanglah tuduhan. Pertama soal LHKPN, karena ayam hias tidak masuk laporan. Penjelasan Idris sederhana: ayam adalah makhluk hidup, bisa mati kapan saja, nilainya tidak tetap. Yang dilaporkan adalah kandang, karena itu aset fisik. Aturannya memang begitu, dan tidak ada yang dilanggar. Kedua, soal isu sabung ayam di Raja Laut Farm. Tuduhan ini berulang kali dilempar, tapi tak pernah disertai bukti. Idris menegaskan farm itu tempat pembiakan ayam kontes, bukan arena judi. Ia bahkan menantang siapa pun yang bisa membuktikan sebaliknya. Ketiga, isu intervensi rekrutmen PJLP di Kali Adem. Lagi-lagi, ia luruskan: yang ia lakukan adalah memperjuangkan kesempatan kerja bagi warga Pulau Seribu, bukan menitipkan orang di luar aturan.
Kalau mau jujur, semua tuduhan itu berhenti di opini, tidak pernah naik ke level bukti. Sementara kerja-kerja konkret Idris ada jejaknya, baik di berita lokal maupun catatan pemerintahan daerah. Warga yang ia wakili bisa menilai langsung, apakah aspirasinya ditampung dan diperjuangkan, atau tidak.
Inilah paradoks yang harus kita lihat: Idris bukan politisi karir, tapi justru karena itu ia jadi sasaran empuk. Ia masuk ke politik karena desakan rakyat, lalu disambut dengan serangan yang memang jadi bagian dari permainan politik kota. Perlu ditegaskan, kritik itu sah. Tapi kritik tanpa data yang berubah jadi fitnah hanya akan merugikan publik, karena mengaburkan fakta siapa sebenarnya yang bekerja untuk rakyat.
Idris sendiri tidak pernah memposisikan dirinya sebagai tokoh besar. Ia tahu betul kursinya bisa sewaktu-waktu hilang, dan ia tidak rugi apa-apa kalau kembali ke dunia usaha. Yang rugi adalah masyarakat Pulau Seribu, kalau suara mereka hilang dari meja DPRD.
Oleh karena itu, membaca sosok Muhammad Idris seharusnya tidak hanya lewat headline miring. Ia adalah contoh orang yang awalnya enggan masuk politik, tapi maju karena dorongan warga. Ia bekerja dengan cara sederhana: mendengar, mencatat, memperjuangkan. Fitnah boleh datang, tapi rekam jejaknya tidak bisa dihapus.