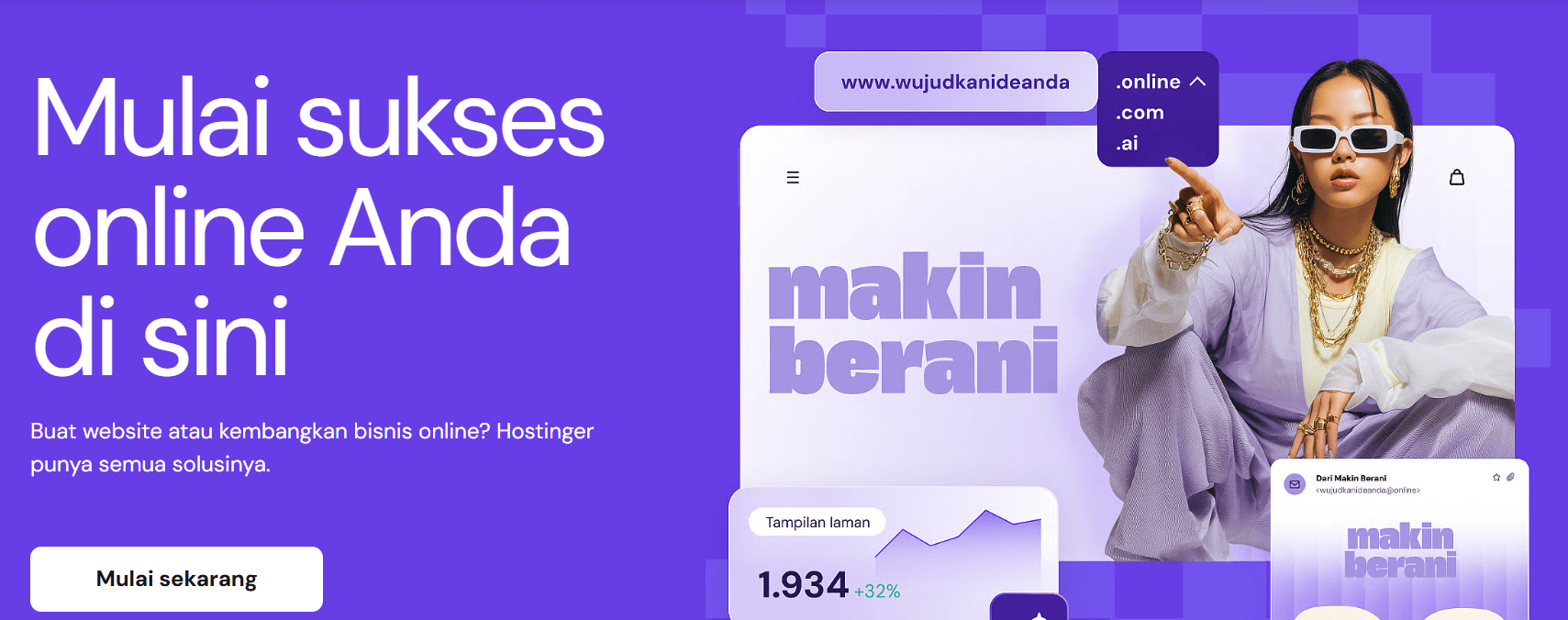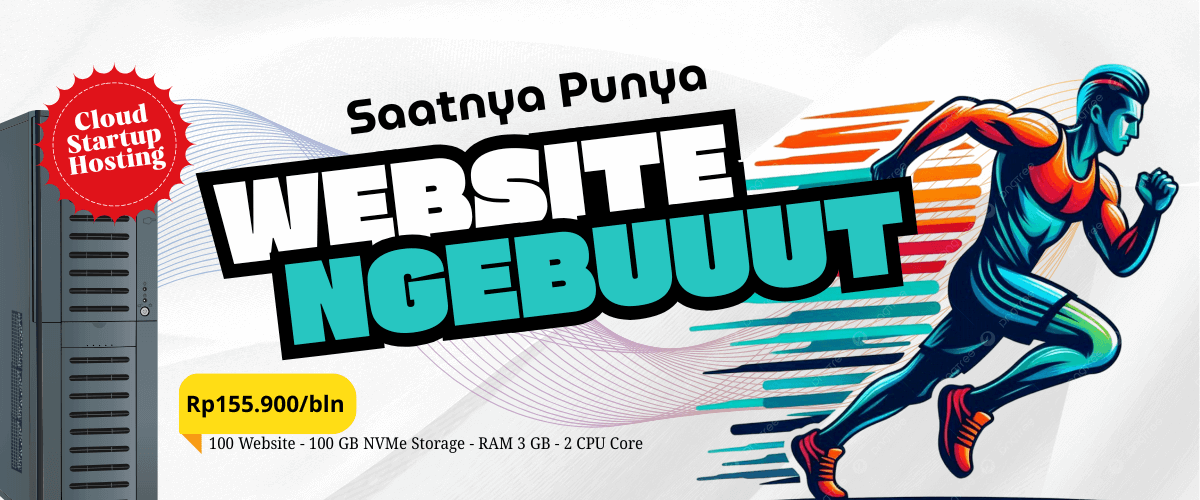JAKARTA – Founder Restorasi Jiwa Indonesia (RJI) Syam Basrijal menjelaskan bahwa ada sebuah kebiasaan yang sangat kentara di depan muka publik, sepertinya merupakan sesuatu yang sangat mulia, namun di sisi lain bisa memiliki daya rusak yang sangat luar biasa. Hal itu ia sebut sebagai toxic charity.
“Ada satu pola kebiasaan yang tampak mulia di permukaan, namun sejatinya beracun bagi jiwa: toxic charity,” kata Syam Basrija, Sabtu (13/8/2025).
Dalam pandangannya, toxic charity adalah sebuah bentuk kebaikan yang salah arah, di mana sebuah aktivitas tersebut justru membuat orang semakin bergantung dan kehilangan daya juang.
Ia tidak sedang menyalahkan kegiatan berbagi dan memberi yang dikenal sebagai core of mentality dari manusia, yakni empati. Hanya saja ketika pemberian itu dilakukan sekadar
“Memberi bantuan instan memang tampak heroik, tetapi jika dilakukan terus-menerus tanpa pendidikan kesadaran, hasilnya bukanlah kemandirian, melainkan ketergantungan yang kronis,” ujarnya.
Syam mengingatkan, bahwa toxic charity sering lahir dari niat baik yang tidak disertai pandangan jauh ke depan. Semuanya berbasis jangka pendek karena bisa jadi berawal dari empati semata, tanpa ada konstruksi sosial yang jelas.
“Ketika melihat orang miskin, segera diberi uang; ketika melihat anak putus sekolah, langsung diberi sembako. Semua tampak cepat dan praktis, namun sesungguhnya menumbuhkan mental miskin: pola pikir yang terus merasa kurang, lemah, dan harus selalu ditolong,” tutur Syam Basrijal.
Lebih buruk lagi, ia menegaskan bahwa toxic charity dapat melahirkan mental korban, di mana muncul jiwa yang selalu merasa menjadi objek belas kasihan, tanpa berani mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri.
Fenomena yang dapat dijadikan contoh konkret adalah konsep Bantuan Sosial (Bansos) yang terjadi di kalangan masyarakat politik saat ini, khususnya di kalangan pedesaan. Di mana seharusnya menurut Syam, konsep bansos menjadi jaring pengaman darurat bagi kebutuhan jangka pendek masyarakat, kini malah cenderung berubah menjadi candu politik. Dalam jangka panjang, ia mengingatkan ini adalah situasi yang sangat berbahaya bagi mentalitas bangsa Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah.
“Alih-alih memberdayakan rakyat, ia menjadikan mereka pasif menunggu kapan bantuan berikutnya datang. Budaya ini secara halus mencetak generasi yang terbiasa menengadah, bukan berani berdiri. Di sinilah racun toxic charity bekerja, pelan tapi pasti melemahkan martabat,” terangnya.
Padahal kata Syam, martabat manusia tidak pernah lahir dari belas kasihan. Martabat hanya tumbuh dari kesadaran akan kekuatan diri. Ketika seseorang terlalu lama diberi tanpa dilatih, daya juangnya mati. Ia kehilangan kreativitas untuk mencari jalan, kehilangan keberanian untuk gagal, kehilangan keyakinan bahwa dirinya mampu. Inilah bahaya paling besar dari toxic charity: ia membunuh potensi sebelum sempat tumbuh.
Dalam perspektif itu, Restorasi Jiwa Indonesia menilai toxic charity wajib ditolak karena akan berangsur menjadi budaya yang tidak baik bagi masyarakat. Maka perlu ada kesadaran kolektif yang lebih holistik dari seluruh unsur bangsa Indonesia untuk meningkatkan literasi jiwa dalam rangka menjadi upaya menebarkan narasi restoratif.
“Melalui narasi restoratif, kami menyembuhkan luka lama. Melalui gagasan transformatif, kami mengguncang paradigma lama yang membuat orang merasa kecil. Dengan literasi jiwa, pemberdayaan menjadi nyata, karena orang tidak hanya diberi ‘ikan’, tetapi diajarkan cara ‘memancing’ dengan kesadaran baru,” jelas Syam Basrijal.
“Kami hadir bukan untuk menenangkan luka dengan perban sementara, tetapi untuk menyentuh akar persoalan. Kami percaya bahwa setiap jiwa diciptakan kaya: kaya ide, kaya cinta, kaya harapan, dan kaya keberanian. Kekayaan itu hanya bisa muncul bila pola pikir yang melemahkan diubah menjadi pola pikir yang memberdayakan. Dan perubahan itu tidak lahir dari belas kasihan instan, melainkan dari literasi jiwa yang restoratif,” sambungnya.