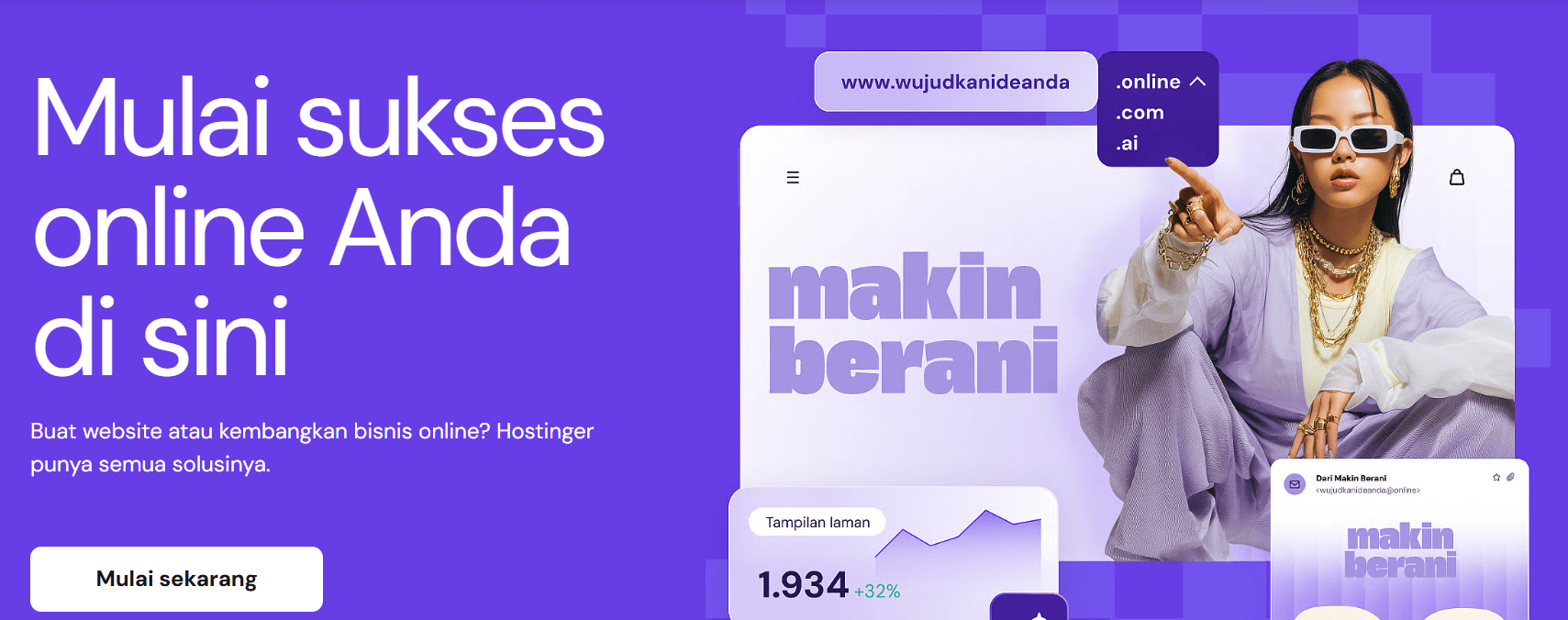PERDEBATAN antara pendekatan ekonomi yang hari ini dikenal sebagai Prabowonomics dan pemikiran ekonomi Mohammad Hatta sejatinya bukan sekadar perbandingan dua tokoh. Ia merupakan refleksi dari dua konteks sejarah yang berbeda, namun sama-sama berpijak pada sumber normatif yang sama: Pasal 33 UUD 1945. Keduanya lahir dari kegelisahan atas ketidakadilan struktur ekonomi, tetapi dirumuskan dalam lanskap geopolitik yang sangat berbeda.
Pemikiran Bung Hatta tumbuh dari pengalaman kolonialisme langsung. Ia menyaksikan bagaimana struktur ekonomi kolonial membentuk ketergantungan sistemik, memusatkan kepemilikan alat produksi pada segelintir elite, serta mereduksi rakyat menjadi objek eksploitasi ekonomi. Karena itu, bagi Hatta, kemerdekaan politik tidak pernah cukup tanpa kemerdekaan ekonomi. Demokrasi ekonomi menjadi fondasi, dan koperasi diposisikan sebagai manifestasi kelembagaan dari kedaulatan rakyat di bidang ekonomi—bukan sekadar bentuk usaha, melainkan ekspresi ideologis dari cita-cita keadilan sosial.
Sebaliknya, Prabowonomics lahir bukan dari situasi penjajahan formal, melainkan dari dunia pascakolonial yang secara struktural tetap timpang. Tantangan yang dihadapi bukan lagi kolonialisme klasik, melainkan dominasi rantai pasok global, ketergantungan pangan dan energi, fragmentasi geopolitik, rivalitas kekuatan besar, serta risiko deindustrialisasi di negara berkembang. Dalam konteks ini, Prabowonomics berangkat dari kegelisahan strategis: bagaimana memastikan Indonesia tidak sekadar menjadi pasar dan pemasok bahan mentah dalam tatanan ekonomi global yang semakin kompetitif.
Perbedaan konteks inilah yang menjelaskan mengapa Hatta berbicara tentang pembebasan rakyat, sementara Prabowo berbicara tentang ketahanan negara.
Paradigma Filosofis: Demokrasi Ekonomi vs Ketahanan Negara
Secara filosofis, perbedaan paling mendasar terletak pada titik tolak analisis masing-masing. Bung Hatta memulai dari premis bahwa kedaulatan sejati hanya mungkin terwujud apabila rakyat menguasai alat produksi. Oleh sebab itu, koperasi, kemandirian desa, dan penguatan ekonomi rakyat bukan sekadar instrumen teknis, melainkan ekspresi ideologis dari demokrasi ekonomi. Negara, dalam pandangan Hatta, berperan sebagai fasilitator dan pelindung kepentingan rakyat, bukan sebagai aktor dominan yang menggantikan peran masyarakat dalam aktivitas ekonomi.
Sebaliknya, Prabowonomics berangkat dari asumsi bahwa dunia hari ini adalah arena kompetisi keras antarnegara. Dalam lanskap semacam ini, negara yang lemah secara ekonomi akan kehilangan kedaulatannya secara politik. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil cenderung bersifat state-centered, dengan penekanan pada peran negara yang kuat, penguatan BUMN, hilirisasi industri strategis, serta intervensi aktif dalam sektor pangan, energi, dan industri.
Perbedaan ini dapat diringkas secara sederhana: Hatta menekankan transformasi dari bawah (bottom-up) melalui kedaulatan rakyat dalam ekonomi, sementara Prabowo menekankan konsolidasi dari atas (top-down) melalui penguatan negara sebagai pelindung kepentingan nasional. Keduanya sama-sama nasionalis, tetapi menempuh jalur strategis yang berbeda.
Di sinilah sekaligus mulai tampak kelemahan struktural Prabowonomics. Pendekatan yang menempatkan negara sebagai aktor utama memang menawarkan kecepatan dan daya kendali, namun juga membawa risiko sentralisasi kekuasaan ekonomi. Tanpa mekanisme partisipasi ekonomi yang luas, penguatan negara dapat menciptakan jarak antara kebijakan makro dan pengalaman ekonomi rakyat sehari-hari. Negara yang kuat secara institusional belum tentu identik dengan rakyat yang berdaulat secara ekonomi.
Konteks Geopolitik Global: Nasionalisme Ekonomi sebagai Arus Baru Dunia
Prabowonomics tidak dapat dipahami secara memadai tanpa menempatkannya dalam konteks geopolitik global kontemporer. Dunia telah bergerak menjauh dari optimisme globalisasi liberal era 1990–2010 menuju fase baru yang ditandai oleh konflik terbuka dan fragmentasi struktural. Pertumbuhan perdagangan dunia melambat tajam, sementara pertimbangan keamanan nasional semakin mendominasi kebijakan ekonomi negara-negara besar. Fenomena yang kerap disebut sebagai slowbalisation atau fragmentasi geoekonomi ini menandai berakhirnya era pasar global yang sepenuhnya terbuka.
Dalam konteks ini, banyak negara justru kembali mengadopsi nasionalisme ekonomi: Amerika Serikat memperkuat proteksi industri strategis melalui kebijakan subsidi besar-besaran; Tiongkok mengembangkan strategi dual circulation untuk mengurangi ketergantungan eksternal; India mengusung agenda Atmanirbhar Bharat; sementara Rusia mengonsolidasikan ekonomi domestik berbasis logika keamanan nasional. Prabowonomics dapat dibaca sebagai respons Indonesia terhadap arus global ini: negara tidak lagi bisa bersikap pasif terhadap mekanisme pasar global, melainkan harus aktif membangun kedaulatan pangan, energi, dan industri.
Namun, nasionalisme ekonomi ini membawa dilema. Ketika negara mengambil peran dominan dalam produksi dan distribusi, muncul pertanyaan mendasar: apakah kekuatan negara tersebut akan diterjemahkan menjadi kekuatan rakyat, atau justru berhenti pada konsolidasi elite ekonomi dan politik?
Hilirisasi, BUMN, dan Batas Nasionalisme Ekonomi
Kebijakan hilirisasi sering diposisikan sebagai pilar utama Prabowonomics. Secara makro, hilirisasi berhasil meningkatkan nilai ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya di sektor mineral strategis. Namun, peningkatan nilai tambah nasional tidak otomatis mencerminkan pemerataan penguasaan modal, transfer teknologi, maupun penciptaan lapangan kerja yang inklusif.
Hilirisasi yang sangat padat modal cenderung menguntungkan aktor-aktor besar yang memiliki akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan jaringan global. Tanpa desain kelembagaan yang secara sadar melibatkan koperasi, UMKM, dan tenaga kerja lokal sebagai subjek utama, hilirisasi berisiko menjadi nasionalisme produksi tanpa demokratisasi kepemilikan. Kritik Bung Hatta mengenai penguasaan alat produksi menemukan relevansinya kembali di titik ini.
Hal serupa berlaku pada penguatan BUMN. Aset dan peran BUMN memang meningkat signifikan, tetapi keterkaitannya dengan ekonomi rakyat masih terbatas. Tanpa akuntabilitas publik yang kuat dan orientasi distribusi manfaat yang jelas, penguatan BUMN dapat menjelma menjadi state capitalism without social ownership—negara kuat, tetapi rakyat tetap menjadi penonton.
Kelemahan Struktural Prabowonomics
Selain risiko sentralisasi, Prabowonomics juga menghadapi persoalan keberlanjutan fiskal. Intervensi negara berskala besar memerlukan kapasitas pembiayaan jangka panjang, sementara basis penerimaan negara masih relatif sempit. Ketergantungan pada belanja negara tanpa perluasan basis produksi rakyat berpotensi menciptakan tekanan fiskal di masa depan.
Lebih jauh, dalam konteks kelembagaan Indonesia, penguatan peran negara tanpa reformasi tata kelola membuka ruang oligarkisasi kebijakan. Relasi antara kekuasaan politik dan modal besar berpotensi semakin erat ketika negara menjadi aktor ekonomi dominan. Tanpa transparansi dan kontrol publik, nasionalisme ekonomi dapat bertransformasi menjadi nasionalisme elite—bertentangan dengan tujuan keadilan sosial yang dijadikannya legitimasi.
Kelemahan paling fundamental Prabowonomics adalah belum tampaknya arsitektur kelembagaan yang secara sistematis menempatkan ekonomi rakyat sebagai pilar utama pembangunan. Koperasi dan ekonomi desa kerap hadir dalam wacana, tetapi belum menjadi fondasi struktural industrialisasi nasional. Tanpa institusi ekonomi rakyat yang kuat, penguatan negara berisiko berhenti pada level kebijakan, bukan transformasi sosial-ekonomi.
Relevansi Kritik Bung Hatta dalam Konteks Kontemporer
Di titik inilah pemikiran Bung Hatta kembali relevan sebagai kritik normatif sekaligus parameter kebijakan. Hatta mengingatkan bahwa negara bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memperluas kedaulatan rakyat. Demokrasi ekonomi tidak menolak negara yang kuat, tetapi menolak negara yang menggantikan peran rakyat dalam menguasai proses produksi.
Pertanyaan-pertanyaan kunci yang diajukan Hatta menjadi sangat konkret dalam konteks Prabowonomics: apakah penguatan industri strategis memperkuat posisi petani dan buruh, atau terutama menguntungkan korporasi besar? Apakah program pangan nasional membangun ekosistem koperasi dan ekonomi desa, atau sekadar menciptakan pasar baru bagi kontraktor? Apakah BUMN menjadi instrumen kedaulatan rakyat, atau wahana akumulasi elite?
Sintesis Strategis: Ekonomi Konstitusi di Tengah Dunia yang Terfragmentasi
Meskipun berbeda secara metodologis, terdapat benang merah yang kuat antara Prabowonomics dan pemikiran Bung Hatta. Keduanya menolak liberalisme pasar murni dan sama-sama menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan pembangunan. Keduanya sepakat bahwa sektor-sektor strategis tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, sintesis antara kedua pendekatan justru menjadi kebutuhan strategis. Negara perlu kuat agar tidak tunduk pada tekanan eksternal, tetapi kekuatan tersebut harus diarahkan untuk memperluas—bukan mempersempit—kedaulatan rakyat. Tanpa dimensi Hatta, Prabowonomics berisiko tereduksi menjadi nasionalisme elite. Sebaliknya, tanpa dimensi Prabowo, pemikiran Hatta berisiko terjebak dalam idealisme normatif yang tidak memiliki daya tahan strategis.
Kesimpulan
Perbedaan antara Prabowonomics dan pemikiran Bung Hatta bukanlah perbedaan antara benar dan salah, melainkan refleksi dari dua konteks sejarah yang berbeda. Hatta berbicara dari dunia yang masih dijajah, sehingga fokusnya adalah pembebasan rakyat dari struktur eksploitasi. Prabowo berbicara dari dunia yang terfragmentasi dan kompetitif, sehingga fokusnya adalah memperkuat negara agar tidak menjadi korban struktur global.
Masa depan Indonesia membutuhkan keduanya sekaligus: negara yang kuat tanpa kehilangan orientasi kerakyatan, serta rakyat yang berdaya tanpa kehilangan perlindungan negara. Jika Prabowonomics mampu mentransformasikan kekuatan negara menjadi penguatan koperasi, desa, petani, buruh, dan kelas menengah produktif, maka ia bukan antitesis dari pemikiran Bung Hatta, melainkan artikulasi baru dari ekonomi konstitusional Indonesia di abad ke-21.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukanlah apakah Indonesia harus memilih Prabowonomics atau pemikiran Bung Hatta, melainkan siapa yang benar-benar diuntungkan oleh kekuatan negara yang sedang dibangun. Negara yang kuat tetapi jauh dari rakyat hanya akan melahirkan stabilitas semu; sebaliknya, ekonomi kerakyatan tanpa perlindungan negara hanya akan menjadi romantisme di tengah kompetisi global yang brutal. Di titik inilah Pasal 33 UUD 1945 kembali menuntut keberanian politik: bukan sekadar menafsirkan konstitusi sebagai legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai kompas moral pembangunan.