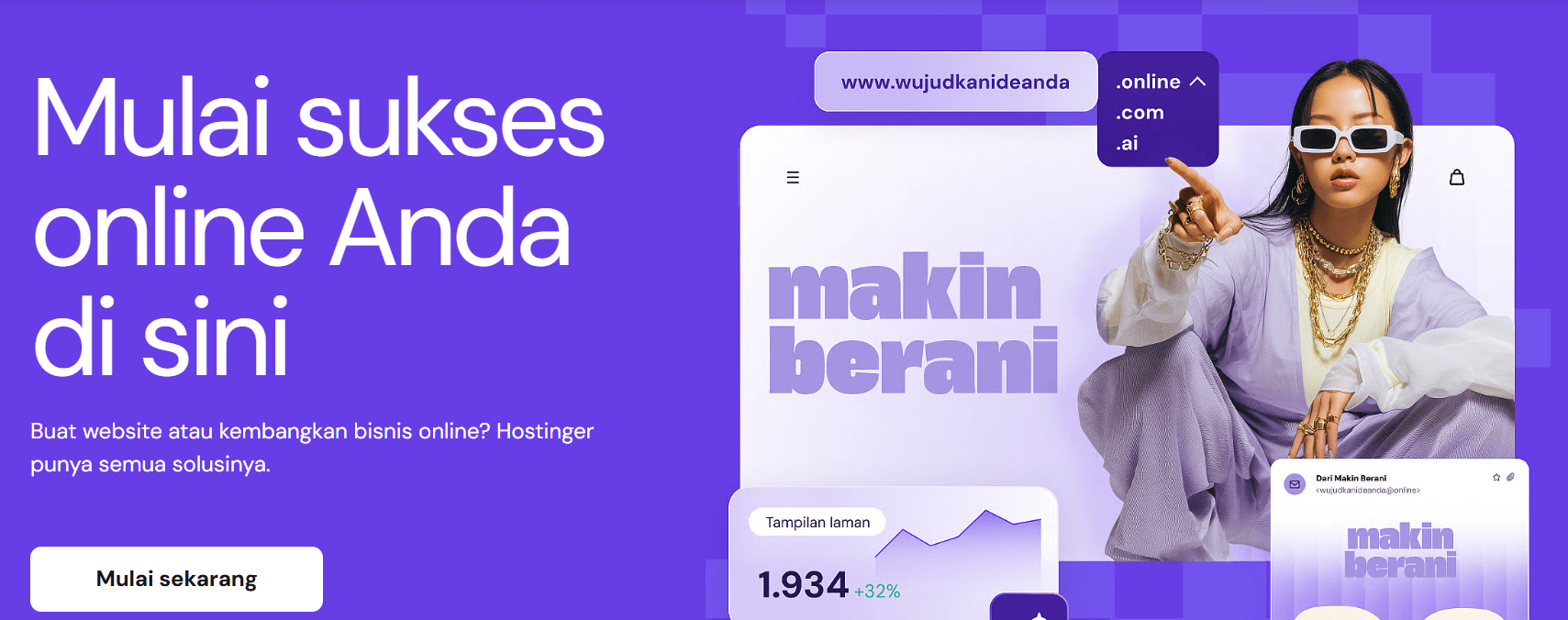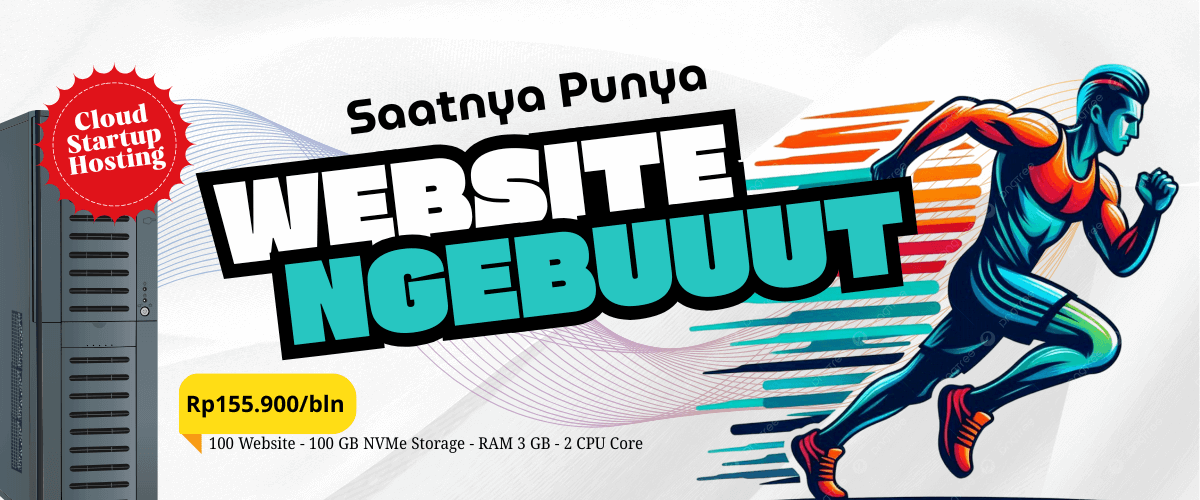HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, bahwa wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD tidak sejalan dengan kondisi politik hari ini, ketika partisipasi publik justru sedang ramai-ramainya di ruang digital.
Di saat masyarakat aktif bersuara, mengkritik kebijakan, dan mengawasi kekuasaan lewat media sosial, mekanisme pilkada justru ingin dipersempit.
Arifki mengatakan, bahwa ruang digital telah mengubah warga dari sekadar pemilih lima tahunan menjadi aktor politik harian. Publik kini ikut menilai rekam jejak, membandingkan kinerja, dan memberi penilaian langsung kepada elite politik secara real time. Politik tidak lagi berhenti di bilik suara.
“Situasinya seperti ini, stadion sedang penuh dan penonton ramai bersorak, tapi justru mikrofonnya dimatikan,” kata Arifki dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Senin (22/12/2025).
Menurut Arifki, pilkada lewat DPRD memang sah secara aturan, tetapi rawan kehilangan legitimasi di mata publik. Kepala daerah yang dipilih elite akan tetap diuji setiap hari oleh masyarakat yang merasa tidak ikut menentukan. Secara hukum bisa sah, tapi secara sosial mudah goyah.
Alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang kerap digunakan untuk membenarkan pilkada tidak langsung dinilai keliru sasaran.
“Masalahnya bukan rakyat terlalu ramai, tapi negara belum siap mengelola keramaian itu,” ujarnya.
Demokrasi, menurutnya, bukan soal membuat politik sunyi, melainkan mengatur suara publik agar tetap sehat. Ironinya, elite politik justru sangat aktif menggunakan media sosial untuk membangun citra dan membaca arah dukungan. Publik dirangkul saat kampanye narasi, namun dikesampingkan saat keputusan diambil.
“Rakyat diperlakukan seperti penonton polling, bukan pemilik suara,” lanjutnya.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini menegaskan, polemik pilkada lewat DPRD bukan sekadar soal mekanisme pemilihan, melainkan soal arah demokrasi ke depan. Di era digital, legitimasi tidak cukup lahir dari prosedur, tetapi dari rasa dilibatkan.
“Jika jarak antara keputusan elite dan harapan publik terus dibiarkan, demokrasi lokal bisa tetap berjalan secara administratif, namun kehilangan ruhnya—seperti panggung megah tanpa penonton,” pungkas Arifki.