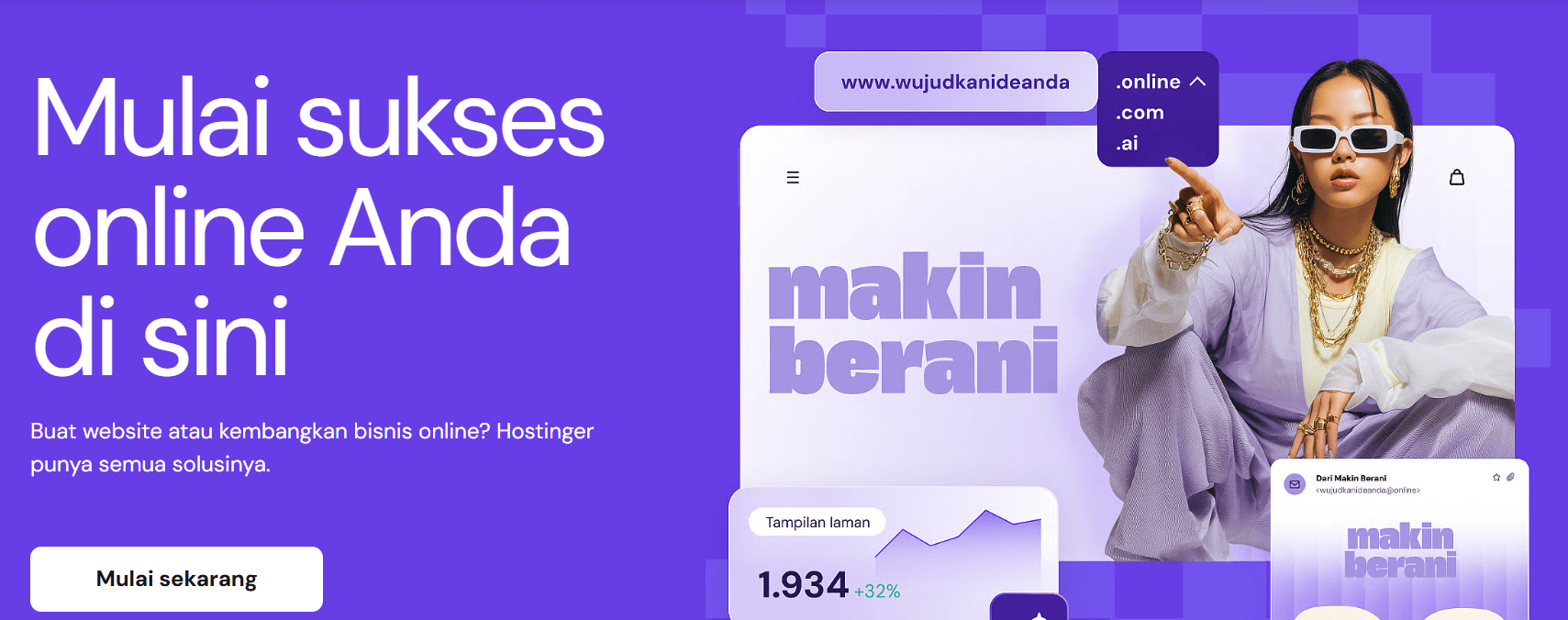Mahasiswa sering dihubungkan dengan semangat muda, keberhasilan, dan kerja keras yang terus-menerus. Dalam pandangan masyarakat, mahasiswa yang ideal adalah individu yang terlibat aktif di organisasi, berhasil dalam akademik, ikut serta dalam berbagai kompetisi, dan tetap dapat memelihara citra positif di media sosial. Harapan yang sangat besar ini selanjutnya menciptakan norma baru mengenai “mahasiswa luar biasa”, individu yang terlihat aktif, efisien, dan sukses dalam berbagai aspek. Namun, di balik pencapaian tersebut, banyak mahasiswa yang sebenarnya berjuang secara diam-diam untuk menjaga kesehatan mentalnya di tengah tuntutan untuk terus menjadi “lebih baik”.
Lingkungan sosial yang penuh kompetisi, tekanan akademik yang tinggi, dan dampak media sosial membuat mahasiswa berada dalam keadaan yang bertentangan. Mereka diharapkan untuk berhasil, tetapi jarang mendapatkan kesempatan untuk gagal atau beristirahat. Sering kali, masyarakat menilai keberhasilan mahasiswa hanya berdasarkan IPK, pencapaian yang tercatat, dan tingkat kesibukan mereka di lingkungan kampus. Meskipun begitu, tidak semua jenis aktivitas memiliki hubungan langsung dengan kesehatan mental. Di tengah tuntutan itu, muncul dilema besar yang dihadapi banyak mahasiswa terkait bagaimana cara tetap produktif, mengejar cita-cita, tetapi tetap menjaga kesehatan mental?
Menjadi individu yang memiliki berbagai pencapaian tentu sangat membanggakan. Namun, saat produktivitas dijadikan satu-satunya ukuran untuk mengukur keberhasilan, maka mahasiswa akan terjebak dalam siklus tekanan dan perbandingan sosial. Media sosial memperburuk situasi ini dengan menyajikan gambaran “kesuksesan semu” , posting tentang kompetisi yang dimenangkan, magang bergengsi, atau usaha yang sedang berkembang , tanpa menunjukkan usaha, keletihan, atau kecemasan yang terjadi di baliknya.
Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), lebih dari 60% mahasiswa di Indonesia mengakui sering melakukan perbandingan diri dengan orang lain di media sosial, dan hampir setengahnya merasa kurang percaya diri terhadap kemampuan pribadi setelah melihat prestasi rekan-rekannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya produktivitas telah berubah menjadi “perlombaan eksistensi”, di mana mahasiswa bersaing untuk tampak mengesankan ketimbang benar-benar tumbuh sesuai potensi mereka.
Ambisi sejatinya merupakan energi positif yang mendorong individu untuk berusaha meraih tujuan. Namun, ambisi yang berlebihan bisa menjadi dua sisi mata yang tajam. Mahasiswa yang memiliki ambisi tinggi sering kali tidak mau beristirahat, mengakumulasi aktivitas, dan mengabaikan kebutuhan dasar seperti tidur atau bersantai. Dalam jangka waktu yang panjang, ini menyebabkan kelelahan emosional, stres berkepanjangan, dan gangguan kecemasan.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI (2023) menunjukkan bahwa 38% mahasiswa mengalami stres akademik dengan intensitas sedang hingga tinggi, sedangkan 21% di antaranya menunjukkan gejala kelelahan mental karena tekanan akademik dan sosial. Data ini menunjukkan bahwa meskipun kampus berfungsi sebagai fasilitas pengembangan potensi, banyak mahasiswa malah mengalami ketidakseimbangan hidup dan masalah kesehatan mental.
Ironisnya, sistem pendidikan tinggi juga secara tak sadar memperkuat budaya produktivitas yang ekstrem ini. Banyak institusi pendidikan tinggi mengharuskan mahasiswanya memiliki “portofolio hebat” agar dapat bersaing di dunia kerja, namun tidak secara serius menyediakan dukungan fasilitas kesehatan mental yang memadai. Sebagai akibatnya, mahasiswa berjuang sendiri menghadapi tekanan yang rumit , mulai dari akademik, keluarga, hingga sosial , tanpa tempat aman untuk beristirahat dan berbagi cerita.
Kesehatan mental bukanlah berlawanan dengan produktivitas, melainkan dasar yang mendukungnya. Mahasiswa yang memiliki kesehatan emosional yang baik cenderung lebih konsentrasi, memiliki ketahanan akademik yang lebih tinggi, serta mampu berpikir inovatif dalam menghadapi masalah. Sebaliknya, mahasiswa yang merasa lelah sering kali kehilangan semangat, menunda pekerjaan (prokrastinasi), dan tidak dapat menikmati proses pembelajaran.
Sayangnya, masih banyak orang yang melihat istirahat sebagai tanda ketidakaktifan. Sebenarnya, istirahat merupakan elemen dari produktivitas yang terus-menerus. Mengelola waktu, memahami batasan diri, dan menyediakan kesempatan untuk beristirahat justru mendukung seseorang agar tetap seimbang secara emosional. Mahasiswa harus menyadari bahwa keyakinan untuk menjadi unggul tidak harus selalu melibatkan usaha tanpa akhir.
Hebat adalah saat seseorang dapat mengatur waktunya dengan baik, menjaga keseimbangan antara ambisi dan akal sehat, serta menyadari kapan harus berhenti untuk mengambil napas.
Mahasiswa juga perlu meningkatkan kesadaran diri , kemampuan untuk menyadari kapan dirinya merasa lelah, cemas, atau kehilangan arah. Tanpa menyadari hal ini, mereka akan terus berada dalam lingkaran perfeksionisme dan kelelahan yang tidak pernah berakhir. Menurut Prayitno (2017) dalam buku Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, keseimbangan pribadi adalah faktor penting dalam proses pembelajaran yang sehat dan bermakna.
Keseimbangan antara efisiensi dan kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab pribadi, melainkan juga institusi pendidikan dan komunitas. Kampus harus membangun ekosistem yang mendukung, di mana mahasiswa dihargai tidak hanya karena pencapaiannya, tetapi juga karena proses dan sifat yang mereka kembangkan.
Penerapan program kesehatan mental, seperti konseling tanpa biaya, kelompok diskusi psikologis, dan pelatihan pengelolaan stres, sangat penting. Sebaliknya, dosen dan pihak universitas juga perlu merubah cara pandang penilaian , tidak semua mahasiswa harus terlibat dalam setiap aspek untuk dianggap memiliki potensi. Kadang-kadang, menjadi mahasiswa yang konsentrasi, sabar, dan seimbang justru mencerminkan tingkat kedewasaan yang lebih tinggi.
Lebih dari itu, masyarakat perlu menghentikan tekanan terhadap mahasiswa dengan harapan yang terlalu tinggi. Ungkapan seperti “kamu harus sukses dalam kuliah” atau “perhatikan temanmu, dia sudah meraih banyak prestasi” sering kali terdengar sepele, tetapi bagi mahasiswa yang berjuang, ungkapan tersebut dapat menjadi penyebab stres. Apa yang diperlukan oleh mahasiswa bukan sekadar motivasi, melainkan juga empati dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanpa adanya tekanan yang membelenggu.
Dilema antara ambisi, produktivitas, dan kewarasan adalah cerminan zaman yang mengharuskan “berlari cepat tanpa henti untuk berpikir.” Mahasiswa saat ini perlu menyadari bahwa kesuksesan sejati tidak diukur berdasarkan seberapa padat atau terkenal mereka, melainkan seberapa utuh diri mereka menjalani proses tersebut.
Menjadi mahasiswa yang seimbang bukan berarti mengorbankan semangat atau ambisi, melainkan justru menunjukkan kedewasaan emosional untuk mengenali batas diri dan kebutuhan pribadi.
Penyelesaian dari permasalahan ini tidak hanya berasal dari orang per orang, tetapi juga dari sistem yang menjalaninya. Mahasiswa harus mengembangkan kebiasaan merenung, menerapkan pengelolaan waktu yang praktis, serta berani berhenti sejenak saat merasakan kejenuhan. Sementara itu, pihak universitas harus memperluas akses layanan konseling, menyelenggarakan seminar kesehatan mental, dan membangun budaya akademik yang lebih manusiawi.
Saatnya kita merubah pemahaman mengenai makna keberhasilan. Mahasiswa yang luar biasa bukanlah yang selalu terbaik di semua bidang, melainkan mereka yang dapat berkembang dengan kesadaran, berpikir jelas, memiliki mental yang tangguh, dan tetap peka terhadap diri sendiri serta lingkungan. Sebab pada akhirnya, gelar dan prestasi tidak akan berarti tanpa keseimbangan batin.
Dan mungkin, di tengah kesadaran untuk beristirahat dan menjaga keseimbangan mental, seorang mahasiswa menemukan bentuk produktivitas yang paling sejati: menjadi individu yang utuh, berdaya, dan bahagia.