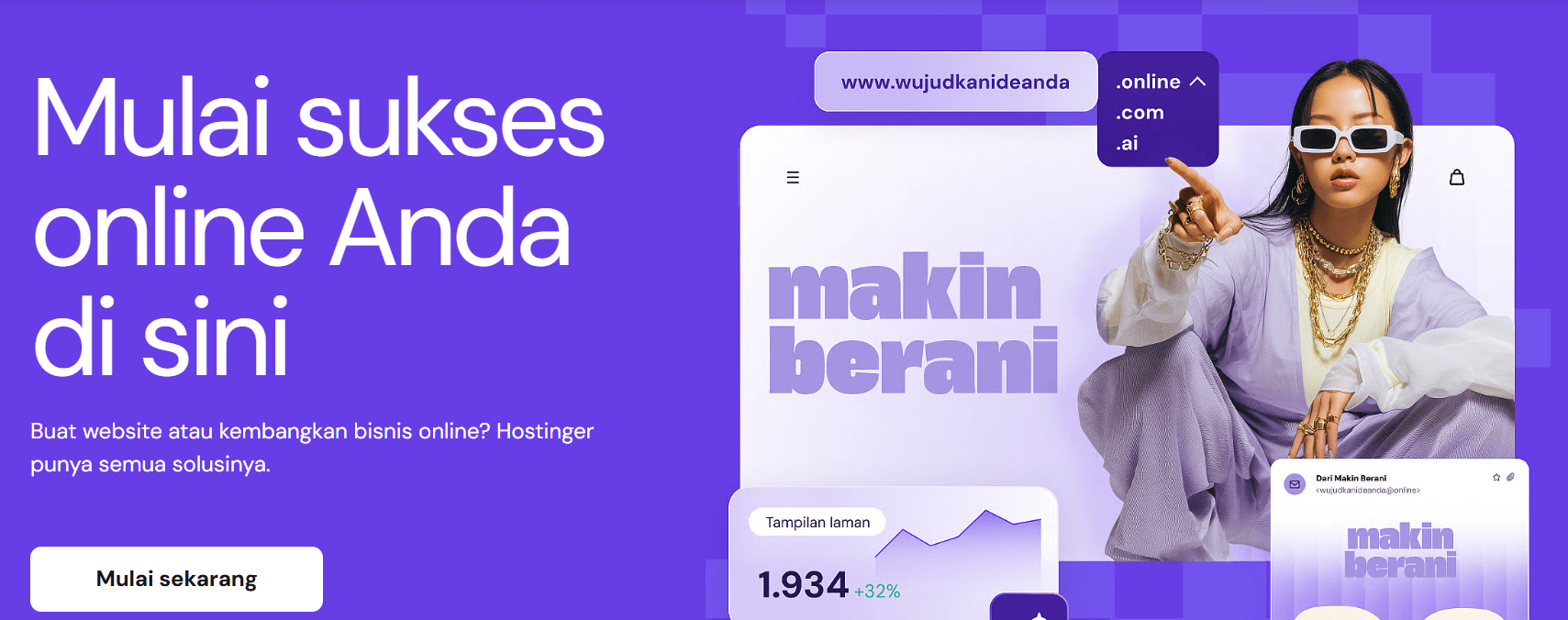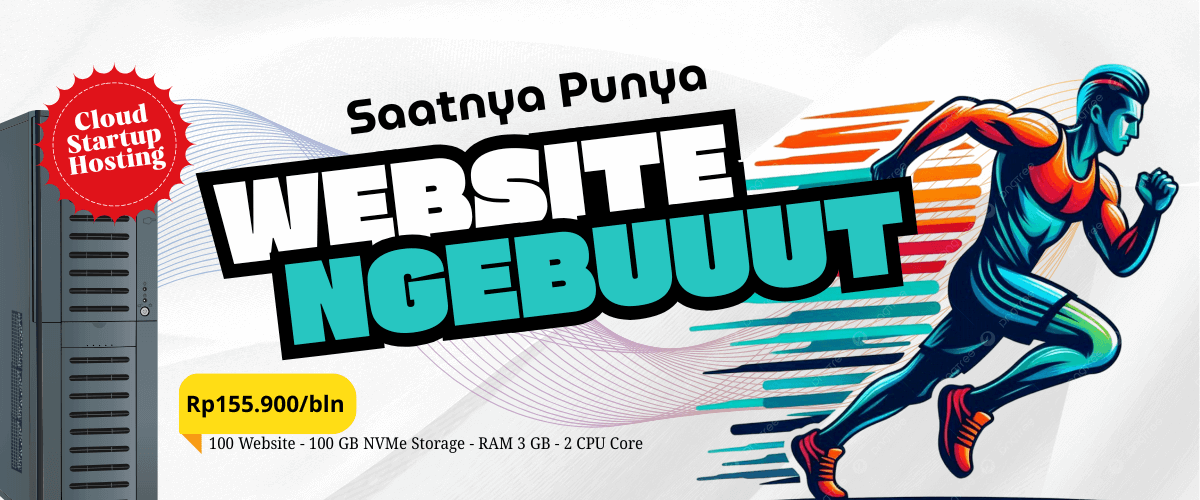HOLOPIS.COM, JAKARTA – Penyebutan istilah hari Arafah pada asalnya adalah untuk tanggal, bukan pada tempat ataupun aktivitas tertentu. Hari Arafah adalah tanggal sembilan Dzulhijah, baik ada yang wukuf ataupun tidak, baik ada yang puasa ataupun tidak.
“Karena penyebutan nama hari jika pada nama hari-hari dalam sepekan maka maksudnya adalah benar-benar nama hari tersebut secara hakiki. Umpamanya ‘yaum isnaen‘ artinya Hari Senin, tidak ada kaitannya dengan tanggal. Hari Senin bisa tanggal berapa saja,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), KH Jeje Zaenudin dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Sabtu (24/6).
Tetapi jika disebut nama hari yang bukan kepada nama hari yang tujuh dalam seminggu itu maknanya adalah tanggal. Umpamanya dikatakan, “ayyamul bid” (hari-hari purnama) maksudnya adalah tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan; “yaum tarwiyah” artinya tanggal delapan Dzulhijah, “yaum tasyrik” artinya tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, tidak peduli ia jatuh pada hari apa saja.
“Maka demikian juga jika dikatakan ‘shaum yaum arafah‘ maksudnya puasa tanggal sembilan dzulhijah, tidak peduli jatuh pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at, Sabtu, ataupun Ahad,” ujarnya.
Ajengan Jeje menjelaskan, perintah puasa Arafah adalah shaum yaum ‘arafah. Artinya, puasa pada hari ‘Arafah, bukan puasa karena adanya perbuatan jamaah haji yang sedang melaksanakan wukuf di ‘Arafah, bukan pula puasa karena tempat ‘Arafah. Ia pun meminta ummat untuk memperhatikan perbedaannya dengan cermat, karena di sinilah letak perselisihannya.
“Sebab jika ‘Arafah sebagai tempat dan sebagai aktivitas wukuf menjadi syaratnya, maka puasa Arafah hanya ada jika ada yang wukuf di ‘Arafah. Padahal syariat ibadah shaum Arafah berlaku baik ada yang sedang wukuf ataupun tidak ada yang wukuf,” jelas dia.
Maka pelaksanaan wukufnya jamaah haji dan keberadaan tanah Arafah, tidak termasuk ke dalam rukun, syarat, sabab, maupun mâni’ dari adanya perintah dan pelaksanaan puasa Arafah. Seandainya puasa Arafah dikaitkan secara langsung dengan aktivitas wukufnya jamaah haji ataupun karena keberadaan tempat Arafah, mestilah ia menjadi salah satu bagian dari terlaksananya hukum taklify.
“Apakah ia sebagai syarat, rukun, atau sabab? Atau jika tidak ada yang wukuf menjadi penghalang (mâni’) terlaksananya puasa Arafah. Pada faktanya tidak ada satupun dalil bahkan fatwa ulama sekalipun, yang menjadikan aktivitas wukuf sebagai rukun, syarat, maupun sabab pensyariatan puasa Arafah,” tuturnya.
Ia melanjutkan bahwa puasa ‘Arafah sudah disyariatkan sejak tahun kedua Hijrah sedang syariat ibadah haji baru pada tahun ke enam atau ke sembilan Hijrah. Jadi selama empat atau tujuh tahun, kaum muslimin puasa ‘Arafah tanpa memperhatikan kapan jamaah haji wukuf, atau tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya yang wukuf di ‘Arafah.
“Pelaksanaan puasa ‘Arafah dengan tidak memperhatikan penanggalan setempat akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih sulit, yaitu penentuan hari lebaran Idul Adha nya. Kalau memang ada dalil yang diperselisihkan tentang pengertian puasa ‘Arafah, apakah untuk Idul Adhanya juga harus mengikuti penanggalan Saudi?,” tanyanya.
“Maka akan terjadi kekacauan penanggalan bulan Dzulhijah selanjutnya yaitu setelah tanggal sepuluh. Kecuali kalau mau konsisten untuk sepanjang tahun tidak menggunakan penanggalan negeri masing-masing tetapi menggunakan penanggalan tunggal mengikuti hasil ru’yat Saudi dengan konsekuensi negeri-negeri muslim seluruh dunia tidak akan punya kalender melainkan menunggu ketetapan ru’yat Negara Saudi pada setiap awal bulan,” jelasnya.
Baca selengkapnya di halaman kedua.