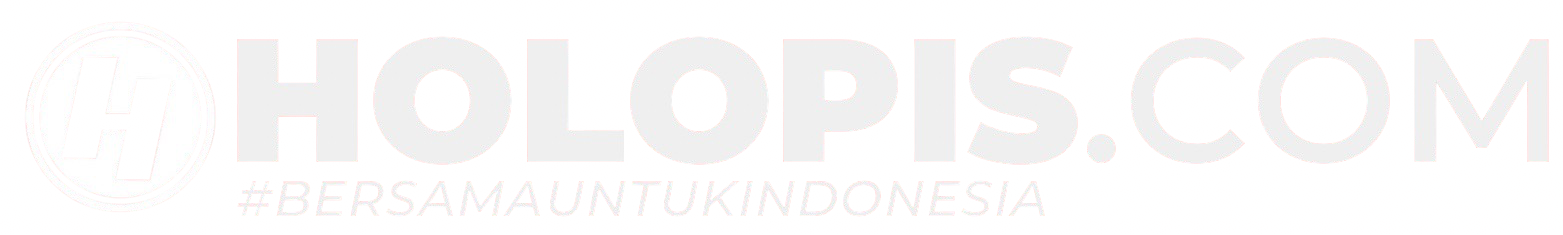Unggahan di media sosial dari seorang profesor ahli kimia di sebuah kampus ternama di Yogyakarta mengenai Ade Armando berbuntut pelaporan kepada pihak polisi.
Menurut berkas kepolisian yang banyak beredar di media sosial, pelaporan tersebut diajukan oleh pelapor pada tanggal 18 April 2022 dengan keterangan bahwa terlapor melakukan “penghasutan dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau ujaran kebencian melalui media elektronik”.
Menurut keterangan pelapor yang disampaikan melalui media sosial, pelapor merasa terancam akibat unggahan terlapor yang menempatkan fotonya bersama Ade Armando. Sementara foto Ade Armando diberi tanda silang (X). Selain terpampang foto dia, terdapat juga foto isteri pelapor dan beberapa orang lain.
Lebih-lebih di situ juga diberi pernyataan “satu persatu dicicil massa”.
Unggahan akademisi yang memiliki latar pendidikan par-excellence dari kampus ternama di dalam dan luar negeri tersebut seolah membuat geleng-geleng kepala publik, termasuk sebagian akademisi dari kampusnya sendiri.
Keheranannya adalah mengapa seseorang dengan gelar yang sangat terhormat di perguruan tinggi sampai mengumbar istilah yang mengandung ancaman dan kekerasan verbal/visual.
Jauh sebelum kasus ini mengemuka, sebenarnya cukup banyak muncul ujaran kebencian atau setidaknya pernyataan dengan kekerasan verbal dari kalangan akademisi.
Intoleransi di Kalangan Akademisi
Pertanyaan yang perlu kita ajukan dalam mendiskusikan masalah ini adalah seberapa besar sebenarnya akademisi yang memiliki sikap intoleran dalam melihat perbedaan, misalnya perbedaan orientasi politik atau perbedaan agama. Lebih dari itu juga dalam aspek-aspek apa intoleransi itu berkembang.
Berbagai studi menyebutkan bahwa sebagian sekolah dan universitas menjadi ekosistem berkembangnnya pemahaman intoleran.
Di jurusan dan fakultas eksakta baik pada level SMA maupun level perguruan tinggi, matrik berpikir yang hitam-putih dan salah-benar secara clear-cut turut mendorong sikap-sikap intoleransi tersebut.
Selama ini kebanyakan riset tentang sikap intoleransi di lembaga pendidikan terfokus pada kajian mengenai pandangan dan perilaku siswa atau mahasiswa. Jika pun ada riset tentang pendidik, seringnya kajian mengenai sikap atau perilaku guru di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Kita sangat beruntung pada tahun lalu, 2021, ada riset yang cukup ekstensif mengenai sikap toleransi atau intoleransi di kalangan dosen di perguruan tinggi.
Penelitian tersebut dilakukan oleh Yunita Faela Nisa, dkk. dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta yang diterbitkan dengan judul Kebinekaan di Menara Gading, Toleransi Beragama di Perguruan Tigggi (PPIM, 2021).
Selain mengkaji pandangan dan sikap toleransi mahasiswa, penelitian itu juga memberikan perhatian khusus terhadap pandangan dan sikap toleransi dosen.
Penelitian Yunita, dkk. mendefinisikan toleransi sebagai “kesediaan seseorang untuk menerima hak-hak sipil individu atau kelompok agama lain yang tidak disukai atau tidak disetujui”. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Pertama, kemauan untuk menghargai pernyataan atau perilaku mereka yang tidak disukai/ disetujui. Kedua, pola hubungan dengan pihak lain yang berbeda agama. Ketiga, sikap mengenai hak-hak sipil kelompok agama lain dalam konteks kehidupan bernegara.
Melalui survei terhadap 542 dosen dengan latar multi agama di 86 perguruan tinggi, penelitian tersebut secara umum mengungkapkan dari skala 0-100, sikap toleransi dosen di Indonesia rata-rata berada pada angka 60.89. Secara sekilas tampak temuannya mayoritas dosen bersikap toleran.
Tetapi dalam penghitungan lain di riset itu disimpulkan bahwa sepertiga dosen di perguruan tinggi kita masih memiliki tingkat toleransi yang relatif rendah atau sangat rendah. Sepertiga ini adalah jumlah yang cukup besar.
Kita bisa membayangkan pernyataan yang mengandung ancaman dari satu dosen saja di media sosial dapat menghebohkan, seperti disinggung di muka. Apalagi jika sikap intoleransi dari sepertiga dosen manifes di dalam kehidupan kita.
Pada aspek apa toleransi tersebut rendah? Temuan riset ini menunjukkan intoleransi pada umumnya memiliki dimensi politik. Dalam aspek politik lebih dari 50 persen dosen masih memiliki sikap toleransi yang tergolong rendah atau sangat rendah. Secara umum dosen-dosen belum siap untuk mentolerir hak-hak politik serta peran politik yang lebih besar bagi pemeluk agama yang paling tidak disukai.
Sementara itu dalam aspek interaksi sosial para dosen di Indonesia cenderung lebih toleran. Sikap toleransi politik yang lebih rendah jika pada akhirnya ditotal menurunkan tingkat sikap toleransi dosen secara keseluruhan seperti angka di atas.
Diantara pertanyaan yang diajukan dalam riset itu terdapat dua yang menarik kita cermati.
Pertama, meskipun tidak ada responden yang mengaku pernah menandatangani petisi untuk melarang penggunaan simbol-simbol agama dari kelompok yang paling tidak disukai di ruang publik, mereka mengaku memiliki niat untuk melakukan perbuatan itu jika memiliki kesempatan di masa yang akan datang.
Kedua, sebagian besar responden tidak pernah dan tidak berniat untuk berdemonstrasi menentang kelompok agama yang paling tidak disukai. Meskipun demikian, sebagian kecil responden Muslim (14.4%) dan Protestan (7.5%) mengaku berniat untuk melakukan tindakan tersebut jika mereka memiliki kesempatan di masa yang akan datang. Sebagian kecil responden dosen Muslim mengaku pernah berdemonstrasi menentang kelompok agama yang paling tidak disukai.
Sampai di sini, kita mungkin sepakat bahwa pekerjaan rumah kita mengenai pengembangan sikap-sikap toleransi di lembaga pendidikan masih menjadi PR besar kita bersama.
Selama ini asumsi kita melihat kebutuhan itu ada di level siswa atau mahasiswa. Penelitian di atas menunjukkan sebenarnya terdapat juga kebutuhan di tingkat dosen. Tentu pendekatan yang digunakan perlu strategis.
Lebih dari itu, penting juga mempertimbangkan aspek-aspek politik-ekonomi dalam persoalan berkembangnya sikap intoleransi di kalangan dosen, supaya kita lebih teliti lagi membaca masalah ini dan tidak memunculkan sikap-sikap yang kotra produktif.
Komunikasi di Media Sosial
Pertanyaan lain yang mungkin ada di benak kita adalah mengapa seorang dosen atau akademisi yang berpendidikan tinggi masih sering terjebak dalam komunikasi yang tidak patut di media sosial?
Dalam menemukan jawabannya, mungkin kita bisa menengok perkembangan awal dari media sosial. Ketika media sosial mulai semarak pada awal tahun 1990an –meskipun belum se-merajalela seperti sekarang, kajian-kajian sosiologis sudah memulai riset-riset empiris mengenai “cyber scope” (John J. Macionis, 1992, 158-159).
Dalam kajian itu kurang lebih persoalan yang diajukan adalah “bagaimana teknologi baru ini mengubah cara hidup kita”.
Saat itu, studi tentang tingkah laku pengguna media online dalam mempersepsi dirinya (the cyber-self) menyimpulkan bahwa seorang pengguna media cyber mentranmisikan dirinya melalui media tersebut sebagai sosok tanpa tubuh (disembodied) (Dennis Waskul, 1997).
Komunikasi daring yang tidak face to face mendorong pengguna media online melepaskan identitas yang menempel pada tubuhnya. Seseorang tidak sadar lagi status sosialnya Ketika berselancar di dunia maya.
Di sisi lain, karena di dunia maya seseorang menghadapi lawan bicaranya tidak secara langsung, dia seolah-olah berbicara kepada khalayak yang tidak dia kenal. Akibatnya dia merasa memiliki kebebasan (freedom) tanpa batas.
Logikanya demikian, jika Anda berbicara dengan subjek yang Anda kenal, apalagi jika Anda memiliki kepentingan dengannya, maka Anda akan lebih berhati-hati. Sebaliknya, jika dengan subjek yang tidak Anda kenal dan Anda tidak memiliki kepentingan, Anda cenderung untuk tidak hati-hati.
Seseorang yang menulis suatu ujaran di internet merasa seolah-olah dia hanya menulis untuk dirinya sendiri, tanpa menghitung khalayak audiennya. Istilah yang popular dalam kajian itu menyebutkan, “Online is a game… Only here, I play with who I am” (Waskul, 1997: 21). Artinya, dia merasa berbicara dengan diri sendiri tanpa mempertimbangkan audien.
Dalam kasus di atas, tidak mengejutkan (meskipun menjengkelkan) apabila terlapor kemudian menyebutkan dalam keterangan lisannya bahwa unggahannya di Facebook hanyalah untuk “bercanda”.
Bagaimana dia bisa menyebut bercanda dalam urusan yang menyangkut ancaman sangat serius seperti itu?
Dalam komunikasi di media sosial, seseorang bisa kehilangan kewarasannya. Dalam berkomunikasi di media sosial, awalnya seseorang merasa yang dihadapannya adalah hanya benda mati berupa layar komputer, laptop, atau telepon selular.
Media sosial mengandung banyak jebakan. Seseorang sering lupa bahwa pada saatnya ujarannya kelak akan dikonsumsi oleh pembaca yang riil, memiliki perasaan, norma, dan seperangkat hukum tertentu.
Karena itu tidak mengherankan jika sering terjadi keterbelahan personal (split of personality) para pengguna media sosial. Dalam kehidupan nyata sehari-hari seseorang bisa jadi memiliki karakter yang sopan, cool, dan toleran, tetapi dalam berkomunikasi di media sosial berubah menjadi kasar, beringas, dan intoleran.
Konsekuensinya, banyak kekacauan yang muncul dipicu dan diawali oleh komunikasi di media online.
Kekacauan-kekacauan itu meski diatasi dan diatur untuk mengurangi merembetnya kekacauan itu di kehidupan nyata sehari-hari seperti sering terjadi di negeri kita belakangan ini.
Tentu banyak orang tidak senaif itu dalam bertingkah-laku di dunia maya. Banyak orang memiliki kesadaran penuh sebagai individu dalam berkomunikasi di dunia maya. Mereka tidak membedakan secara berarti bahasa dan diksi yang digunakan saat berbicara secara daring maupun luring.
UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain, berusaha mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ujaran kebencian dan kekerasan verbal di dunia maya. Peraturan itu menempatkan diantara asas pemanfaatan teknologi informasi adalah “kehati-hatian” dan iktikad baik”, sementara tujuannya memberikan “rasa aman”.
Di situ “pengancaman” merupakan sesuatu yang dilaranng (Pasal 27 (4)). Sementara itu secara detil disebutkan bahwa diantara “perbuatan yang dilarang” adalah “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” (Pasal 28 (2)).
Sampai di sini, selain kita penting mendorong sikap toleransi bagi dosen di perguruan tinggi, tidak kalah pentingnya adalah mendesak mereka untuk bertanggung jawab dalam melakukan komunikasi di media sosial.
Pada gilirannya kebijakan-kebijakan strategis perguruan tinggi dan stakeholdernya penting dikembangkan untuk terus memperbaiki diri supaya perguruan tinggi menjadi rumah bersama yang nyaman bagi putra-putri terbaik bangsa.
Bersamaan dengan itu sudah seharusnya dosen terus menjadi pembelajar sepanjang hidup.