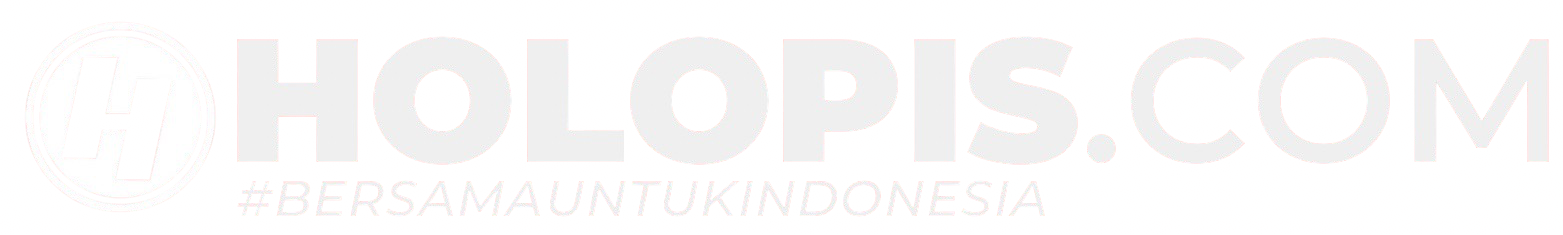Sebenarnya, sesi mengobrol dengan orang-orang usia lanjut tidak terlalu menarik bagiku karena mereka hanyalah sekumpulan orang-orang dengan pemikiran yang agak kuno. Ya jelas, kan mereka hidup lebih dulu dariku di zaman yang tentu belum se-modern ini.
Keluarga dari papaku mempunyai suatu tradisi aneh yang entah apa namanya. Setiap darah daging dari Datuk diwajibkan pergi ke Rumah Jompo alias asrama para tetua (disebut begitu karena memang isinya setara dengan Datuk) untuk diberi nasihat dan ilmu pengetahuan. Minimal satu tahun dua kali. Tradisi ini dilakukan turun-temurun dari para tetua sebelum Datuk, fungsinya agar anak-cucu tidak menyepelekan sejarah-budaya dan bisa mengetahui latar belakang kehidupan orang terdahulu. Menurutku tidak terlalu penting dan sangat-sangat membuang waktu, tetapi seru juga berbincang dengan para orang lansia.
Namun perbincangan malam ini kurasa boleh juga, obrolan yang dibuat tidak terlalu membahas cerita-cerita tentang bagaimana akhirnya Indonesia dapat merdeka dan bebas dari penjajah lalu diikuti dengan nasihat dari tetua lelaki (bukan kakek) bahwa kita harus menghargai jasa para pahlawan, mereka sudah begini dan begitu untuk membuat negaranya kembali aman dan makmur—nasihat ini sudah dikatakan setiap kami bertemu. Beruntung malam ini tetua malah membahas tentang kehidupan orang tuaku saat masih sekolah dulu, menceritakan bagaimana perjalanan mereka, dan bagaimana mereka bisa bersama hingga lahirlah aku.
“Dulu papamu sering nggak dapat uang dari si Abah saat masih di pesantren. Abah kadang lupa untuk mengirimi anak itu karena urusan yang padat dan belum lagi dia harus mengurusi adik adiknya.” Tetua mengatakan itu sambil sesekali mendelik ke arah papaku.
Yang jadi bahan cerita hanya cengar-cengir sementara mamaku menyimak sambil minum teh hangat yang disediakan. Aku sejujurnya bingung hendak merespons apa; yang kulakukan hanya menatap lawan bicaraku agar tidak dikira ‘nggak mendengarkan’, alias takut tetua merasa tidak dihargai olehku. “Tapi papamu ini kreatif, dia berjualan es lilin seharga 25 rupiah di kantin kejujuran”.
“Eh? Terus laku?? ” Ini refleks, aku tau ini tidak sopan tapi sungguh aku refleks bertanya karena di saat rasa kepoku membuncah, maka pertanyaan apa pun di kepalaku bisa keluar secara spontan. Kukira Tetua akan merengut karena aksiku, tapi ternyata beliau malah tertawa. “Esnya habis, tapi uangnya tidak pas.” Lalu ketiganya tertawa.
Kami melanjutkan sesi berwisata masa lalu hingga memasuki pertengahan siang dan sore. Tetua bilang, dulu mama dan papaku bertemu saat keduanya kuliah. Mereka berpacaran saat KKN. Saat papaku tanya bagaimana tetua tahu, beliau hanya menjawab, “Saya tahu semuanya”. Lagi-lagi, aku tidak terlalu peduli mau sampai tetua tahu rahasia kapan kiamat terjadi tapi aku tetap menghargai yang diketahuinya.
Aku kembali ke rumah Datuk, di sana ternyata sudah ramai kembali. Awalnya sepi karena sepupu-sepupuku berpencar ke segala tempat wisata. Mereka menyambutku dan kedua orang tuaku dengar berteriak-teriak, inikah etika menyambut orang yang baru saja datang? Sedikit kesal tapi kucoba untuk santai saja.
“Kakak Emily sudah pulang!!!” teriak saudaraku yang masih TK, namanya Iren. Si pemilik suara cempreng yang membuat gendang telinga kita hampir pecah. Anak itu selalu berhasil dalam hal mengundang keberisikan sekawanannya. Aku tersenyum terpaksa, lalu menyalami mereka satu per satu, begitu juga mama dan papa yang berusaha keluar dari lautan keponakannya. Setelah berhasil, akhirnya aku duduk di samping Ochi –sepupu yang seumuranku. dia bertanya apa saja yang kulakukan di rumah Tetua, “Kayak biasanya sih, tapi yang ini agak beda. Biasanya kan TETUA bahasnya mah penjajahan mulu, lah ini malah bahas kehidupan Papaku waktu masih kruncing”
Ku jejalkan sepotong roti kacang bentuk bulan ke mulutku. Enak. Perpaduan gurih dan manis. “Ya itu sama aja kali Eeemmm, kan Tetua kalo ngga bahas Belanda ya bahas kehidupan orang tua waktu masih susah terus ujung-ujungnya ceramah, for example ‘kalian harus bersyukur hidup di zaman serbaenak seperti sekarang karena blablabla’ —”
“Nggak, Tetua yang tadi enggak ngasih nasihat yang basi, malah Tetua nggak kasih nasihat sama sekali. Itu artinya aku sendiri yang harus menyimpulkan. Tapi aku tetap ditanya gimana kehidupan, gitu”
“Buset, lo ke rumah Tetua yang mana, dah? Enak bener bisa skip nasihat gitu. Padahal kalo kata Datuk, nasihat itu penting untuk meminimalisir potensi kesalahan tersebut agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kalau tidak ada nasihat, orang akan menjadi rusak perbuatan dan pikirannya, dan berpotensi membahayakan diri dan nyawa orang lain.”
Ochi berkata demikian persis seperti yang diucapkan datuk saat SBD alias Sesi Bersama Datuk, baru Sabtu minggu lalu Datuk berkata. “Tapi nasihat nggak harus selalu disampaikan secara detail, kan? Bisa jadi Tetua mau nyampein nasihat lewat cerita, jadi biar kita ikut mikir dan merenung”.
“Iya juga, tapi lo kayaknya lagi hoki banget, ditanyain how’s life tapi nggak dikasih nasihat itu langka sih bagi kita cucu-cucu Datuk”.
Aku tersenyum mengejek, lalu mencomot roti kacang di genggaman Ochi. Dia mencubit lenganku, aku meringis karena memang selain cubitan mama, yang mengerikan adalah dicubit Ochi. “Oh, iya gimana dengan Sleeping Beauty? Udah selesai baca?”.
“Dih, selesai dari zaman aku masih rok merah, ya. Telat banget lo baru nanyain sekarang, itu buku udah aku baca berulang ulang kali sampai sekarang masih jadi buku terfavorit aku dari sekian banyaknya buku yang aku punya” Memang benar. Saat masih kelas 5 SD dulu, Ochi memberiku buku cerita Sleeping Beauty yang kalau dimaknai sekarang itu kisah putri Aurora yang dikutuk. Kasihan, padahal Aurora cantik. Buku itu jelas sudah selesai kubaca satu hari setelah Ochi memberi bukunya sambil meremehkan. Aku masih ingat sekali, dia berkata kalau aku pasti tidak akan bisa selesai membaca buku ini dengan cepat. Nyatanya dia salah.
“Emang masih bagus bukunya?” Ochi mengangkat satu alisnya. “Masih lah, itu buku dapet tahta tertinggi di rak-rakku”
“Kirain udah sobek-sobek, soalnya lo nggak mungkin banget bisa nyimpen sebuah barang selama ini, coba dihitung, dari kelas 5 rok merah sampai lo kelas 11 rok abu abu sekarang berarti 7 tahun lo nyimpen buku itu dan kata lo bukunya masih bagus? Unpredictable”.
Aku memutar bola mata, “Dan pemikiran aku tentang Aurora yang enak banget dikutuk tidur mulu masih sama. Ya lo mikir nggak sih? Enak dong Aurora dikutuk tidur bertahun tahun terus bangun-bangun dia ketemu pangeran cakep kayak idol”.
Ochi kini memutar kepalanya ke arahku lalu memandangku kaget, dia memajukan tubuhnya lebih dekat denganku masih dengan ekspresi kaget.
“Lo baca buku itu berulang ulang tapi masih nggak tahu kisah aslinya?” Aku mengernyit, merasa diremehkan (lagi lagi)
“Aku tau!!!! Aurora emang diperkosa di kisah aslinya dan kebangun bukan karena dikecup pangeran tapi karena bayi yang dilahirin, Dia nyedot ujung jarinya terus kutukannya ilang??!!! I know right?”.
“Terus lo kenapa masih bilang enak jadi Aurora? Diperkosa sama raja biadab, terus selama dia tertidur, dia hamil sampai 9 bulan layaknya ibu hamil di dunia, dan lo masih berasumsi enak jadi Aurora? Hah?”.
Diam. Aku diam karena merasa skakmat dengan perkataan Ochi. Itu benar, aku memang patut disalahkan karena masih berasumsi kalau enak sekali rasanya jadi Aurora. Tapi maksudku bukan Aurora versi kisah nyatanya, versi dibuku itu yang kumaksud. “Kalo dipikir dari kisah aslinya Aurora dari dia lahir sampai gede hidupnya merana banget sih, kayak sama sekali nggak ada happy-nya”.
“Ya lo bayangin aja, kecil baru lahir udah dikutuk terus umur 17 tahun ketusuk jarum—menurut aku itu sakit sih tapi mungkin sama Aurora nggak kerasa karena dia langsung tidur setelah kena jarum”.
Ochi diam lalu aku ikut diam. Saat ini benar-benar tidak ada yang bicara, yang terdengar justru suara teriakan sahut-menyahut dari dapur, Nin dan Datuk sedang berdebat mengenai hidung panjang Pinokio. Kami menoleh, kini kami tak fokus berdebat mengenai kisah Aurora si putri tidur yang ternyata malang sekali. Ochi terus memperhatikan Nin dan Datuk, sementara aku bengong tapi telingaku mendengarkan segala perdebatan dengan nama Pinokio.
“Pinokio itu enggak ada!! Itu cuma khayalan Carlo Collodi semata!”. “Tapi dari kisah Pinokio lahirlah Efek Pinokio, kamu pernah baca artikel nggak sih?!!”. Nin menggeram, telinganya merah dan matanya melebar serta tubuhnya terus maju hingga mengenai Datuk. Lawannya mengeluarkan geraman keras, biasanya itu tanda Datuk tidak setuju dengan asumsi yang Nin berikan.
“Saya tahu! Tapi di sini yang kamu percayai itu kisahnya!!! Kesal saya sama kamu”. “Menurutmu aku nggak kesal??!!! Kisah Pinokio si hidung panjang itu beneran ada! Dan memang efek yang diberikan di dunia nyata bukan hidung panjang!!! Tapi suhu di sekitar hidung naik”. Nin sengaja menekan kata “hidung”.
“Saya nggak ngerti kamu ngomong apa! Sudah kepala lima percaya begituan! Norak! Tua jompo jiwa seperti murid TK.”
Aku benar-benar tidak menahan tawaku lagi saat Datuk berkata demikian. Ochi juga. Kami tertawa bersama sampai tidak sadar kalau Nin dan Datuk berjalan ke arah kami sambil masing-masing membawa satu alat dari dapur. Nin membawa spatula sementara Datuk membawa cangkir aluminium berisi kopi jahe panas. Aku dan Ochi berhenti tertawa lalu gugup, Ochi menarik ujung bajuku—dalam artian dia sedang menyalahkanku.
Datuk menatapku nyalang, Nin pun sama menatap Ochi sambil mengangkat spatulanya tinggi-tinggi. Beberapa detik kami beradu tatapan hingga akhirnya Nin berteriak, “kalian pilih opsi mana? 1) Pinokio bukan khayalan; 2) Pinokio khayalan Carlo tapi diangkat berdasarkan pengalaman; 3) punya perspektif sendiri”
Kujawab dengan percaya diri kalau sebenarnya Pinokio betul khayalan Carlo Collodi, tapi belum selesai aku bicara Nin memotong.
“Nin tidak setuju”
“Emi bahkan belum selesai bicara, Nin!!”
“Tidak perlu dilanjut. Nin sudah tahu. Pikiranmu sama kolotnya seperti pria di sebelahku” Datuk menoleh. “Pikiranku atau pikiranmu yang kolot? Coba pikirkan secara hati-hati”.
Dan keduanya melanjutkan berdebat, Nin dengan gaya emosinya yang meledak-ledak, Datuk dengan gayanya yang tetap cool dengan kedua tangan di saku celananya. Baik, ini tidak bagus karena mungkin jika anak-anak kecil lewat maka ia akan seperti semut yang melihat gula lalu memberi sinyal kepada kawanannya untuk merapat ke tempat dia berada. Suara Nin dan Datuk lumayan menggema. Nin dan Datuk melakukan sesi yang menurutku tidak penting, yaitu sesi memperdebatkan hal-hal yang seharusnya tidak didebati. Tadi aku juga melakukan sesi itu dengan Ochi, kalau diibaratkan Nin dan Datuk, mungkin posisiku di Nin lalu Ochi di Datuk yang menolak fakta yang kubuat bahwa kehidupan Aurora sangat menyenangkan. Aku menyenderkan bahuku ke pinggir sofa, lalu menyelonjorkan kakiku sambil mendengarkan perdebatan lansia. Sesekali kami tertawa, Nin dan Datuk seakan hanya berdua menganggap kami hanya angin lewat saja. Lalu perdebatan terus berlanjut, ada adegan di mana Nin melempar spatulanya dan Datuk mengetuk-ketukkan gelas aluminiumnya di meja.
Sore ini nama Pinokio mengundang keributan luar biasa yang membuat kemakmuran rumah runtuh.