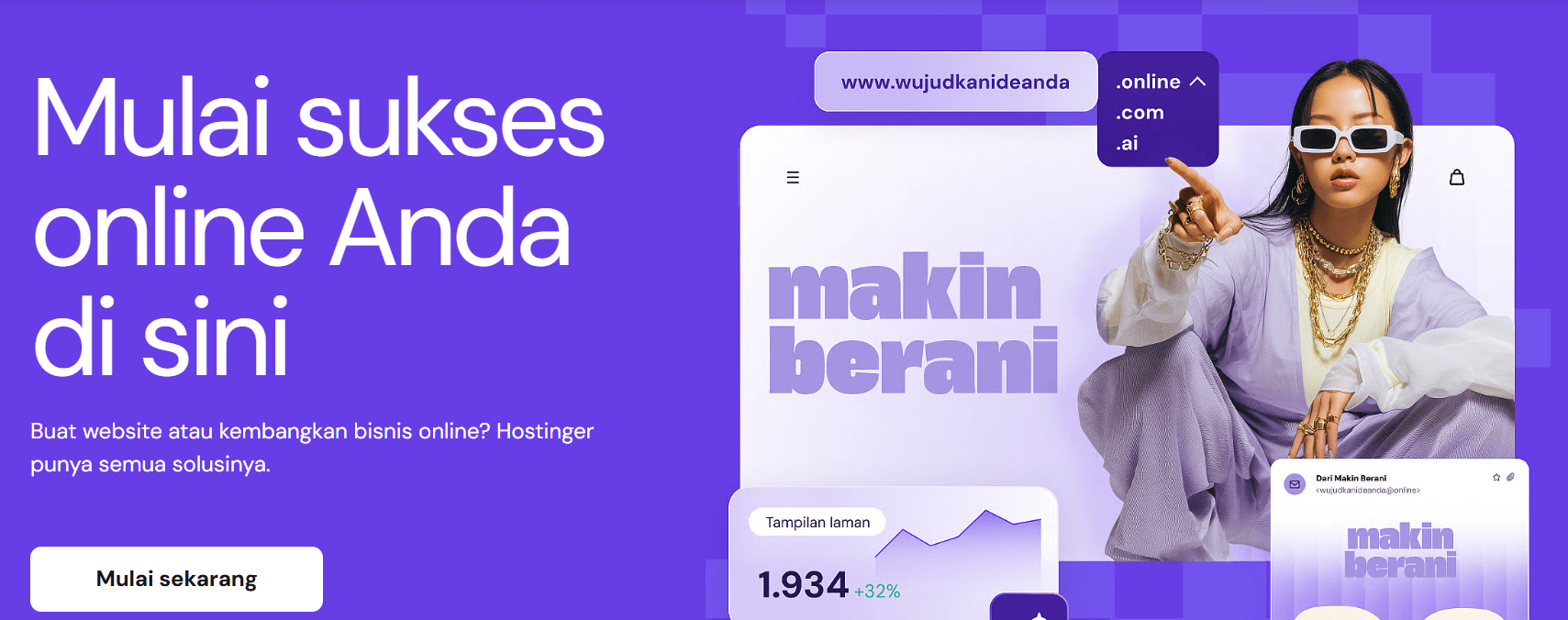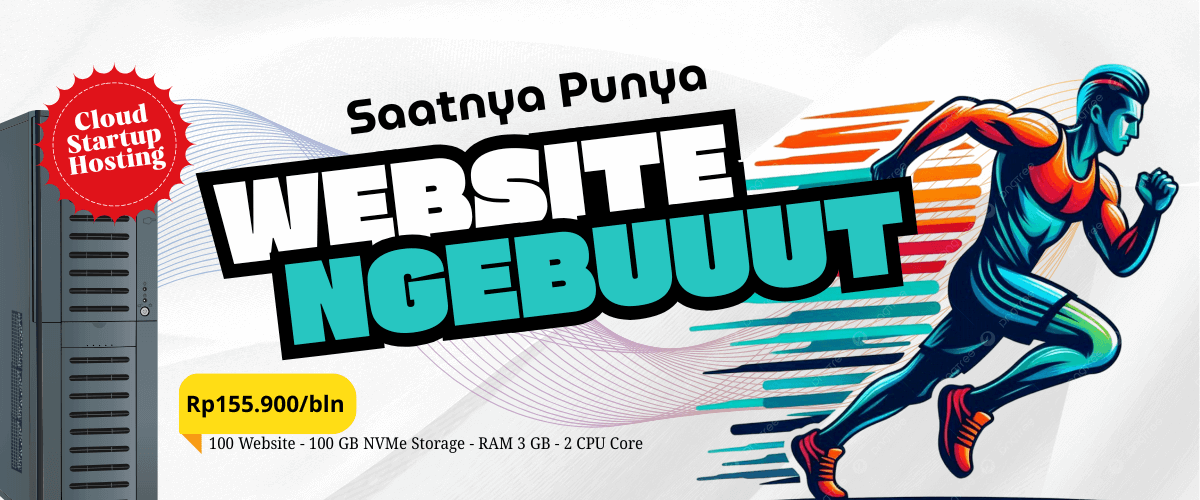HOLOPIS.COM, JAKARTA – Founder Satya Mindcare, Syam Basrijal mengatakan bahwa generasi Z ( Gen Z ) adalah generasi pertama yang sejak kecil hidup dengan layar di tangan. Mereka tidak pernah benar-benar mengenal dunia tanpa notifikasi. Ini yang membuat validitas di media sosial menjadi tolok ukur yang sangat tajam bagi perspektif anak-anak yang lahir di era tahun 1997 – 2012 itu.
“Mereka tumbuh di ruang di mana eksistensi tidak hanya diukur oleh nilai rapor atau prestasi akademik, tetapi juga oleh jumlah likes, views, dan validasi digital,” kata Syam Basrijal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/2/2026).
Dalam memandang Gen Z, Syam menyebut bahwa mereka sebenarnya sedang hidup di dua dunia sekaligus, yakni dunia nyata yang menuntut prestasi, karier, dan stabilitas. Sedangkan dunia yang kedua adalah dunia digital yang menghadirkan standar hidup seolah-olah semua orang selalu berhasil, selalu bahagia, selalu produktif.
Akibat dari situasi tersebut, Syam Basrijal melihat bahwa Gen Z sedang mengalami sebuah kondisi defisit ketenangan yang ia sebut sebagai krisis sunyi. Karena tak jarang Gen Z akan terjebak pada dua dunia yang sangat dilematik.
“Di ruang perbandingan yang tak pernah berhenti itulah krisis sunyi terbentuk,” ujarnya.
Praktisi kesehatan mental ini pun menyebut bahwa Gen Z akan menghadapi dua situasi berat sekaligus, yakni kecemasan yang luar biasa dan berdampak pada lelahnya psikis merea. Dua kombo maut ini disebut Syam sebagai Overthinking and Comparison Fatigue.
“Overthinking bukan sekadar kebiasaan berpikir berlebihan. Ia adalah respons psikologis terhadap tekanan yang terus-menerus. Setiap keputusan kecil—memilih jurusan, pekerjaan, bahkan gaya hidup—terasa seperti taruhan masa depan,” tutur Syam Basrijal.
Di saat yang sama, media sosial memperlihatkan potongan hidup orang lain yang tampak sempurna. Perbandingan ini menciptakan comparison fatigue, kelelahan psikologis akibat terus-menerus merasa tertinggal. Sayangnya secara alamiah, otak manusia tidak dirancang untuk menghadapi situasi pelik tersebut secara sempurna.
“Secara neurologis, otak manusia tidak dirancang untuk membandingkan diri dengan ratusan orang setiap hari. Namun algoritma digital membuat hal itu menjadi rutinitas. Akibatnya, harga diri menjadi rapuh. Identitas dibangun di atas validasi eksternal, bukan kesadaran internal,” jelasnya.
Lebih lanjut, founder Restorasi Jiwa Indonesia ini pun menjelaskan suatu realitas yang sangat patut dipahami oleh Gen Z, khususnya dalam menghadapi dunia digital. Bahwa di dalam kehidupan digital, seluruhnya dikendalikan oleh algoritma.
Algoritma media sosial bekerja dengan logika atensi. Ia mendorong konten yang memicu emosi—kekaguman, iri, marah, atau takut. Konten yang memicu perbandingan sering kali mendapatkan respons lebih besar.
Yang sangat bisa dilihat secara kasat mata adalah, ketika seorang remaja melihat konten kesuksesan finansial instan, tubuhnya merespons dengan dopamin sesaat, tetapi juga kecemasan laten. Ketika ia melihat standar kecantikan yang tidak realistis, harga dirinya tergerus perlahan.
Pada situasi tersebut, kunci sukses agar diri tidak terombang-ambing dalam dunia digital adalah penguatan literasi, khususnya emotional quotient (EQ). Dikatakan Syam Basrijal, literasi emosional ini adalah barrier yang paling ampuh bagi Gen Z saat ini.
“Masalahnya bukan pada teknologi semata. Masalahnya adalah kurangnya literasi emosional untuk mengelola paparan tersebut. Tanpa kemampuan regulasi emosi, algoritma menjadi arsitek kepercayaan diri generasi muda,” tegas Syam Basrijal.
Pola Keluarga yang Belum Adaptif
Di samping itu, Syam juga menyebut bahwa banyak orang tua berasal dari generasi yang tumbuh dalam dunia yang lebih stabil dan linier. Pendidikan dianggap jaminan kerja. Kerja keras dianggap cukup untuk sukses. Dunia hari ini berbeda. Padahal realitasnya, ekonomi lebih kompetitif, teknologi berubah cepat, sehingga karier pun tidak lagi linear.
“Namun sebagian pola pengasuhan masih menggunakan pendekatan lama; tekanan akademik tinggi, minim ruang dialog emosional, dan ekspektasi yang tidak selalu realistis,” tandasnya.
Dampak yang dihasilkan dari pola asu semacam itu akan membuat anak-anak terkesan menyimpan gejolak batinnya sendiri di dalam hati dan pikiran. Karena ketika anak merasa tidak dipahami, ia ternyata tidak selalu memberontak. Kadang ia memilih diam.
“Diam yang panjang inilah yang menjadi krisis sunyi. Generasi ini tidak kekurangan akses informasi. Mereka kekurangan ruang aman untuk mengekspresikan rasa takutnya,” tutur Syam.
Dalam konteks itu, Syam Basrijal ingin mengajak para orangtua agar lebih bijak dalam menyikapi kondisi Gen Z. Jangan sampai sering menuduh mereka manja, rapuh, atau tidak tahan tekanan. Karena bisa jadi itu adalah perspektif yang keliru.
“Mereka bukan lebih lemah. Mereka lebih terpapar. Paparan informasi, paparan perbandingan, paparan ketidakpastian global,” jelasnya.
Sehingga untuk menghadapi anak-anak tersebut, pendekatannya bukan “militeristik” atau “kekerasan”, melainkan pendampingan sehingga anak-anak bisa lebih terbuka dan nyaman untuk berbicara serta bercerita dengan orangtuanya.
“Di tengah tekanan tersebut, mereka tetap berusaha belajar, bekerja, dan membangun masa depan. Yang mereka butuhkan bukan penghakiman, melainkan pendampingan. Di sinilah pendekatan berbasis kesadaran menjadi relevan,” ucap Syam Basrijal.
Ketahanan Sosial Dimulai dari Generasi Ini
Terakhir, Syam Basrijal memberikan penekanan bahwa ketika generasi muda tumbuh dengan kecemasan kronis dan harga diri yang rapuh, maka masa depan bangsa akan dibangun di atas fondasi yang goyah. Sebaliknya, jika mereka memiliki kesadaran diri, regulasi emosi yang sehat, dan ruang dialog yang aman, maka ketahanan sosial akan menguat secara alami.
“Kita tidak bisa menghentikan perkembangan teknologi. Tetapi kita bisa membangun kesadaran yang lebih kuat dari algoritma. Ketahanan sosial masa depan bukan hanya soal kebijakan atau ekonomi. Ia ditentukan oleh kesehatan mental generasi hari ini. Dan generasi ini tidak meminta untuk dimanja. Mereka hanya meminta untuk dipahami,” paparnya.
Oleh sebab itu, Syam Basrijal merasa perlu mengadvokasi kesadaran mental ini agar para generasi muda Indonesia bisa tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan bermental kuat.
“Melalui edukasi yang dibangun oleh Restorasi Jiwa Indonesia dan pendekatan penguatan mental profesional di Satya Mindcare, generasi muda diajak mengenali emosinya, memahami pikirannya, dan membangun identitas yang tidak bergantung pada validasi digital,” terangnya.