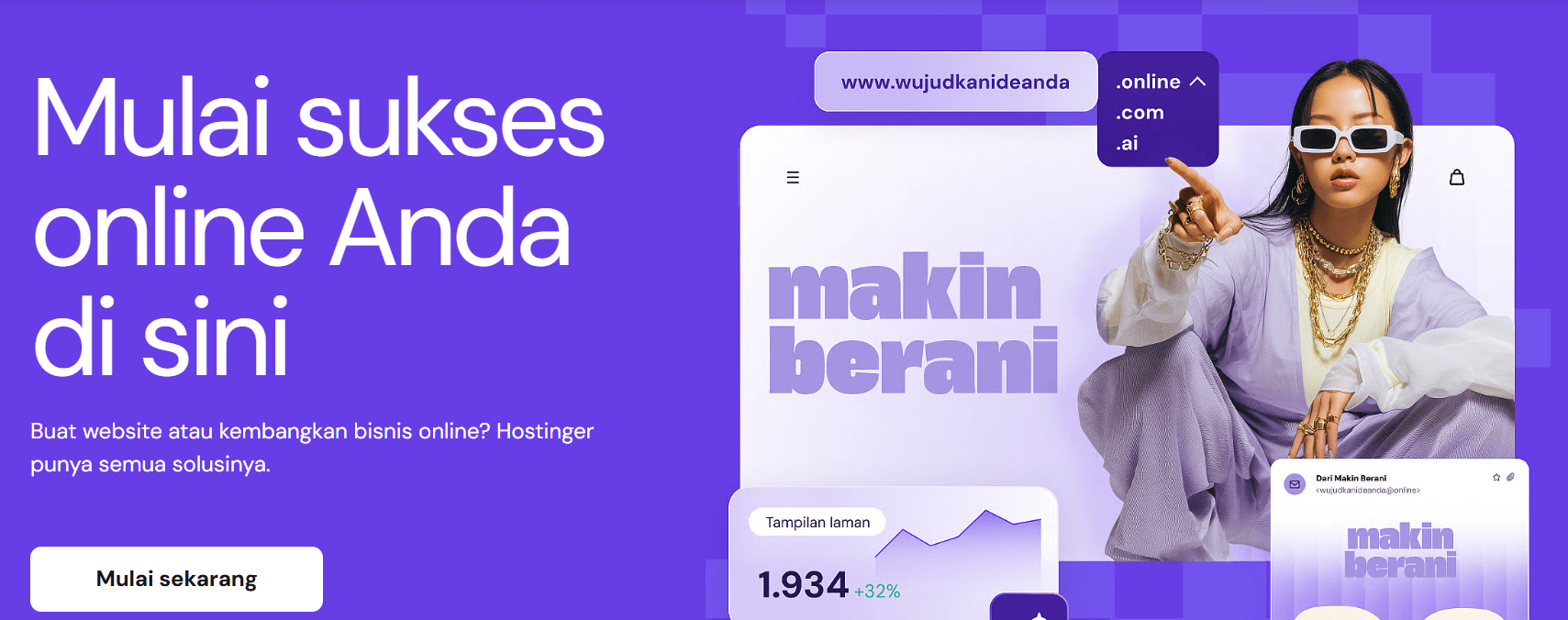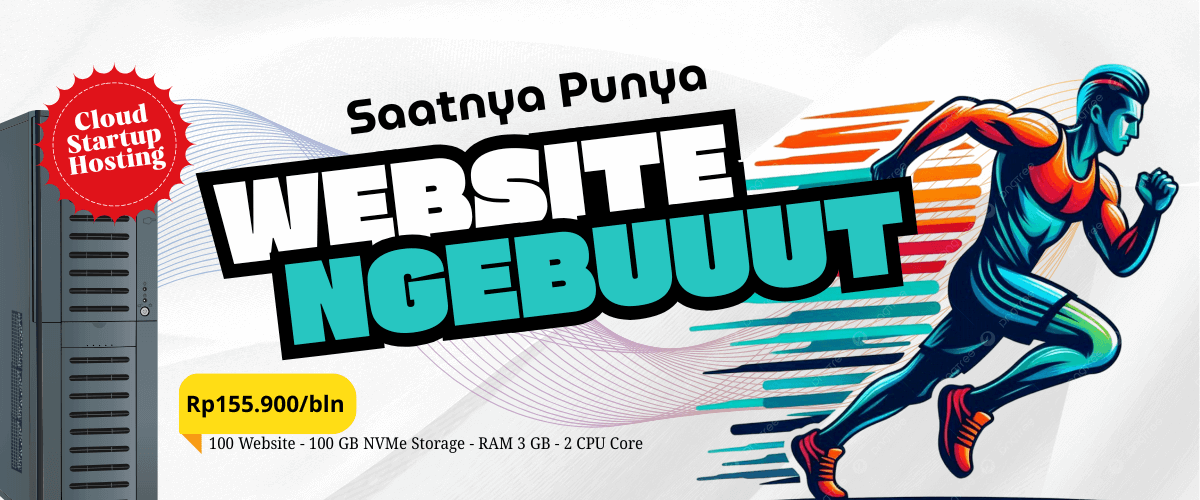HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pendampingan psikologis merupakan aspek krusial dalam penanganan korban bencana, terutama pada fase awal setelah kebutuhan fisik dan medis terpenuhi. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah Psychological First Aid (PFA), metode dukungan psikologis awal yang bertujuan membantu korban kembali merasa aman dan berfungsi secara bertahap.
Psikolog Pengamat Kebencanaan Widura Imam Mustopo menjelaskan bahwa PFA biasanya diberikan setelah bantuan fisik, pangan, dan medis tercukupi. Pada fase tersebut, persoalan psikologis mulai muncul dan perlu ditangani secara tepat.
“PFA diberikan ketika bantuan fisik, pangan, dan medis sudah terpenuhi. Biasanya pada tahap itu masalah psikologis mulai terlihat,” ujar Widura, dikutip Holopis.com, Senin (15/12).
Ia menerangkan bahwa PFA memiliki beberapa skema, dengan model yang paling umum terdiri dari empat langkah utama. Langkah pertama adalah memberikan rasa aman kepada korban. Kedua, membantu korban kembali berfungsi dan produktif secara mandiri. Ketiga, melakukan tindak lanjut apabila korban membutuhkan penanganan lebih spesifik. Keempat, menghubungkan korban dengan akses bantuan lanjutan sesuai kebutuhannya.
“Misalnya korban membutuhkan penanganan yang lebih spesial, kita rujuk ke layanan yang sesuai. Atau jika dia membutuhkan rumah atau bantuan sosial, kita bantu aksesnya,” kata Widura.
Menurut Widura, pemberian rasa aman tidak bisa dilepaskan dari peran lingkungan sosial terdekat. Dalam banyak kasus bencana, korban terpisah dari keluarga atau orang-orang terdekatnya, sehingga reunifikasi menjadi sangat penting.
“Yang paling penting itu mengkolaborasikan orang-orang terdekat. Dalam bencana sering ada yang terpisah, hilang, atau tidak bersama. Kita bantu cari akses supaya mereka bisa berkumpul kembali, karena lingkungan sosial terdekat itulah yang memberi rasa aman,” jelasnya.
Widura menekankan bahwa PFA dapat dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya tenaga profesional, selama dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengarahan awal, terutama bagi relawan dari luar daerah bencana.
“Orang luar yang masuk ke lokasi bencana kadang bingung harus bicara apa. Padahal yang paling penting itu bertanya sederhana, seperti apa kabar. Tidak perlu memaksa korban menceritakan kejadian kemarin,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar menghindari kalimat-kalimat yang terkesan menasihati, namun justru berpotensi menambah beban emosional korban.
“Ucapan seperti ‘sabar ya Bu, ini cobaan’ sebaiknya dihindari, karena justru bisa menambah emosi dan trauma,” katanya.
Widura yang juga merupakan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Jayabaya dan Mantan Ketua Himpsi itu mengatakan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama, terutama ketika korban berada dalam kondisi panik atau stres akut.
“Kalau kita orang awam dan menemukan korban yang panik berat, ngamuk, atau berisiko menyakiti diri sendiri, sebaiknya segera cari tenaga profesional terdekat,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa menghadapi korban trauma bukan hal yang mudah. Namun, jika berada di situasi darurat tanpa pendamping profesional, langkah paling aman adalah menenangkan korban terlebih dahulu.
“Langkah paling aman itu menenangkan. Ketika emosinya bisa ditahan dan dia mulai tenang, barulah pendekatan berikutnya bisa dilakukan,” kata Widura.
Dalam hal identifikasi korban yang membutuhkan dukungan lanjutan, Widura menjelaskan bahwa dalam penanganan bencana besar, tim medis, BNPB, dan SAR umumnya telah melakukan pemetaan awal.
“Dari survei di lapangan, biasanya sekitar 1 sampai 2 persen korban memang memiliki gangguan yang membutuhkan penanganan khusus. Mereka sudah bisa diidentifikasi dan penanganannya berbeda,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa sebagian besar reaksi korban bencana merupakan respons yang wajar. Hal tersebut karena mereka memang memberikan reaksi terhadap situasi yang tidak normal, seperti bencana.
“Dalam situasi abnormal seperti gempa, reaksi apa pun itu normal. Yang penting kita ajak bicara, kita dengarkan, dan kita tanyakan kebutuhannya,” ujarnya.
Tak hanya itu, Widura juga menyebutkan beberapa tanda yang perlu diwaspadai, seperti korban yang tampak diam, kaku, atau mengalami freeze akibat stres berat. Dalam kondisi tersebut, bantuan tambahan mungkin diperlukan. Namun, ia mengingatkan agar tidak terburu-buru memberi label gangguan.
“Manusia punya kemampuan adaptasi. Ada yang cepat, ada yang lama. Ini berkaitan dengan resiliensi,” katanya.
Ia juga menyoroti kebutuhan dasar yang sering terlupakan dalam proses pemulihan psikologis, yakni asupan makan.
“Korban tidak boleh sampai tidak makan. Makan itu penting karena menjadi energi untuk beradaptasi, membangun resiliensi, dan menghadapi tekanan psikologis,” pungkas Widura.